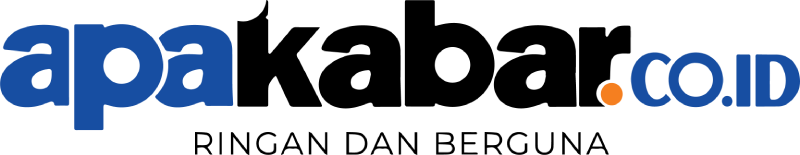Tarif dan Bullying Ekonomi: Dunia Diam, Xi Jinping Menantang!

Oleh: Syafruddin Karimi*
Presiden Donald Trump tidak pernah menyembunyikan pandangannya soal perdagangan. Ia menyebut bahwa tarif adalah “kata terindah dalam kamus”—bukan peace, bukan justice, bukan cooperation, melainkan tariff. Pernyataan ini bukan sekadar lelucon politis, melainkan cerminan dari strategi ekonomi berbasis dominasi.
Saat Trump menaikkan tarif terhadap produk tekstil dan garmen Indonesia hingga 47 persen, dunia menyaksikan kebijakan dagang yang lebih mirip pemaksaan sepihak. Indonesia, sebagai negara berkembang dan eksportir barang padat karya, dipukul keras. Seperti ditulis Nadirsyah Hosen (2025), “rasanya seperti dipalak di muka umum.”
Tarif yang seharusnya menjadi instrumen proteksi atau penerimaan negara, kini berubah menjadi alat economic bullying. Trump tak hanya menggunakannya untuk melindungi industri dalam negeri, tapi juga untuk memaksa puluhan negara tunduk pada kehendaknya.
Dalam pidato publiknya, ia bahkan dengan pongah berkata bahwa “60 countries are coming to kiss my ass.” Kalimat ini bukan saja merendahkan, tapi juga menampar martabat diplomatik negara-negara yang berupaya membuka dialog dagang dengan AS.
Baca juga: TikTok, Trump dan China
Lebih dari enam puluh negara, termasuk sekutu tradisional dan mitra dagang utama, berbaris menghadapi tekanan ini. Sayangnya, banyak dari mereka benar-benar datang—membuka pasar mereka lebih luas, mengurangi surplus perdagangan mereka, dan menerima syarat Trump tanpa perlawanan berarti.
Di tengah barisan negara yang memilih diam atau pasrah, hanya satu pemimpin dunia yang berani menyebut apa adanya: Xi Jinping. Dalam kunjungannya ke Hanoi, ia menyatakan bahwa perang tarif hanya melahirkan kekacauan dan bahwa dunia harus menolak tindakan unilateral dan intimidatif. Xi menggunakan istilah yang tepat—bullying ekonomi—dan menyerukan agar negara-negara menolak tekanan sepihak dari satu kekuatan dominan.
Yang membuat ironi ini semakin kuat adalah asal-usul kata tarif itu sendiri. Seperti dijelaskan oleh Nadirsyah Hosen (2025), kata ini berasal dari bahasa Arab taʿrīf, yang berarti penjelasan atau pemberitahuan.
Dalam sistem perdagangan Kesultanan Utsmani abad ke-16, taʿrīfa merujuk pada daftar tarif bea yang bersifat terbuka dan adil. Pedagang asing dikenai bea masuk sebesar 5–7 persen, non-Muslim lokal 3–4 persen, dan Muslim hanya 2–3 persen. Tarif menjadi sarana distribusi keadilan dan proteksi sosial, bukan alat tekanan politik.
Baca juga: Langkah Politik: Tidak Ada Lagi Teori Ekonomi
Tetapi hari ini, semangat taʿrīf telah terdistorsi. Tarif tidak lagi mencerminkan keterbukaan dan kejelasan, tetapi menjadi simbol dominasi dan subordinasi. Ketika Trump menjadikan tarif sebagai alat pemaksaan global, dan lebih dari enam puluh negara datang dalam posisi lemah, maka yang terjadi adalah penyerahan kedaulatan secara simbolik. Negara-negara yang datang “kissing ass” bukan hanya kehilangan posisi tawar, tapi juga kehilangan harga diri mereka di panggung perdagangan global.
Indonesia tidak boleh masuk ke dalam barisan itu. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki legitimasi moral dan geopolitik untuk menyuarakan prinsip keadilan dalam perdagangan. Kita tidak bisa hanya diam, apalagi pasrah.
Diplomasi ekonomi harus dijalankan dengan keberanian dan arah strategis. Kita perlu memperkuat aliansi dagang yang setara, mendiversifikasi pasar, dan membangun ketahanan ekonomi domestik agar tidak mudah diperas oleh kebijakan luar yang merugikan.
Tarif, pada dasarnya, bukan alat jahat. Ia menjadi masalah ketika dipakai sebagai alat kekuasaan tanpa batas. Ketika sistem multilateral seperti WTO gagal menegakkan aturan main dan memilih bungkam di hadapan Trump, maka negara-negara berkembang harus bersuara lebih keras. Diam hanya akan memperpanjang siklus subordinasi global.
Baca juga: Tarif Ekstra Tinggi dalam Pikiran Trump
Kata taʿrīf pernah berarti keterbukaan dan keteraturan. Tapi kini, ia tampil dalam kostum baru—bernama tariff, dibungkus arogansi, dan dilontarkan dari podium Washington, bukan pelabuhan Istanbul. Sejarah memang tidak pernah mati. Ia hanya mengganti wajah, menyembunyikan maksud lama di balik istilah baru. Di balik kata-kata indah Trump, tersimpan satu pesan jelas: tunduk atau tersingkir.
Kita harus menolak logika semacam ini. Dunia yang adil harus dibangun di atas kesetaraan, bukan di atas rasa takut. Dan perdagangan yang bermartabat harus lahir dari dialog, bukan dari ancaman.
Saatnya Indonesia berbicara—bukan untuk membalas, tetapi untuk mengembalikan makna sejati dari perdagangan: kerja sama, bukan pemaksaan. Karena selama dunia masih membiarkan satu orang menentukan arah globalisasi, maka keadilan hanya akan jadi jargon tanpa isi.
*) Guru Besar Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Andalas
ADMIN