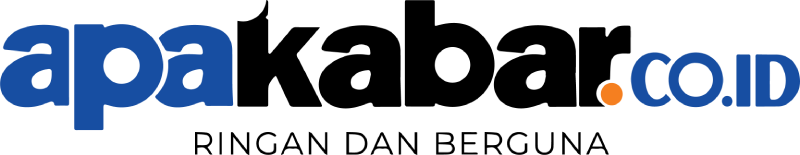UU Kehutanan Dinilai Usang, Koalisi Sipil Tuntut Regulasi Baru

apakabar.co.id, JAKARTA - Wacana revisi Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 yang tengah digodok oleh Komisi IV DPR RI menjadi sorotan tajam koalisi masyarakat sipil.
Dalam konferensi pers daring yang digelar sehari sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Senin (14/7), sejumlah organisasi menyerukan pencabutan total UU lama dan mendesak pembentukan UU Kehutanan baru yang lebih adil, ekologis, dan berpihak pada masyarakat adat.
Koalisi yang terdiri dari Forest Watch Indonesia, WALHI, AMAN, Greenpeace Indonesia, HuMa, Madani Berkelanjutan, Kaoem Telapak, dan Women Research Institute menyebut bahwa UU 41/1999 gagal mengakomodasi dinamika sosial, ekologis, dan konstitusional yang berkembang dalam dua dekade terakhir.
“Sudah waktunya kita mengakhiri tata kelola hutan yang bersumber dari paradigma kolonial. Hutan bukan sekadar aset negara untuk dieksploitasi, melainkan ekosistem hidup yang tak terpisahkan dari masyarakat adat dan lokal,” tegas Anggi Putra Prayoga dari Forest Watch Indonesia.
Koalisi menilai UU 41/1999 telah menyisakan banyak persoalan: konflik tenurial yang terus berulang, minimnya pengakuan atas hutan adat, hingga lemahnya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.
UU ini bahkan telah dibongkar-pasang tujuh kali melalui Perpu, putusan Mahkamah Konstitusi, dan regulasi lain, tanpa menyentuh akar masalah.
Dalam paparannya, Uli Arta Siagian dari WALHI menegaskan bahwa pendekatan teknokratis negara selama ini lebih mengutamakan ekonomi, bukan kelestarian ekosistem atau keadilan sosial.
“Kami dampingi 1,5 juta hektare wilayah kelola rakyat, hanya 16 persen yang diakui dalam 10 tahun terakhir,” ungkapnya.
Sementara Refki Saputra dari Greenpeace Indonesia mengungkap ancaman nyata terhadap 42,6 juta hektare hutan alam di dalam kawasan produksi yang masih bisa dikonversi. Ia juga menyoroti lemahnya moratorium izin sebagai solusi deforestasi.
“Selama paradigma monetisasi hutan tidak diubah, kerusakan akan terus terjadi. UU baru harus tegas menyelamatkan 90 juta hektare hutan alam tersisa dan berpihak pada masyarakat adat,” ujarnya.
Erwin Dwi Kristianto dari HuMa menawarkan arah baru bagi regulasi kehutanan: transisi dari rezim “pengurusan” menjadi rezim “pengelolaan.” Artinya, negara cukup mengelola, bukan menguasai hutan secara mutlak.
“Hari ini kita melihat ironi: kawasan disebut ‘hutan’ walau sudah gundul dan tandus. Ini cacat logika dalam pengurusan negara,” katanya.
Sadam Afian dari Madani menambahkan, UU lama juga tak relevan dengan agenda iklim Indonesia pasca-Paris Agreement. Proyek strategis nasional yang kerap membuka hutan, lanjutnya, harus ditinjau ulang melalui regulasi yang mengutamakan perlindungan ekologis.
Sita Aripurnami dari Women Research Institute menekankan pentingnya inklusi dan perlindungan perempuan serta kelompok rentan dalam UU baru.
Ia mengutip data AMAN: dari 925 kriminalisasi masyarakat adat, dampak terbesar justru ditanggung oleh perempuan yang harus menjadi kepala keluarga sendirian.
“UU baru harus menyertakan klausul kesetaraan gender, partisipasi bermakna, dan mekanisme afirmatif,” kata Sita.
Koalisi merekomendasikan agar DPR menghentikan revisi tambal-sulam terhadap UU 41/1999 dan segera membentuk UU Kehutanan yang baru, sesuai dengan semangat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang mewajibkan partisipasi bermakna dari publik.
“Ini bukan hanya soal hukum kehutanan, tapi tentang masa depan lingkungan, hak masyarakat adat, dan warisan ekologis bangsa,” tutup Patria Rizky dari Kaoem Telapak.
ADMIN