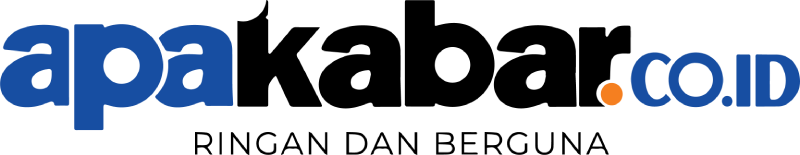Memahami Ukuran Kemiskinan BPS dan Bank Dunia

Oleh: Awalil Rizky*
Banyak komentar negatif terhadap Badan Pusat Statistik (BPS) akibat publikasi Bank Dunia terkini. Salah satu isinya menyebut tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 60,3% dari total penduduk Indonesia tahun 2024, yang artinya sekitar 171 juta orang. Padahal, data BPS menyebut tingkat kemiskinan hanya atau 9,03% per Maret 2024 dan 8,57% per September 2024.
BPS sendiri mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Batas kemampuan itu direpresentasikan oleh Garis Kemiskinan (GK), artinya penduduk miskin adalah orang yang pengeluarannya di bawah garis. Secara teoritis, ditentukan GK terlebih dahulu, kemudian dihitung jumlah penduduk yang berada di bawah dan di atasnya. Penentuannya dimulai dengan GK sementara dan dari data survei dan data penunjang lainnya ditetapkan yang definitif.
Dalam praktik, pengumpulan data penduduk miskin dilakukan secara bersamaan dengan penentuan GK. Hanya urutan pengolahan disesuaikan kerangka teoritis. Penduduk yang disurvei tidak berarti akan seluruhnya berkategori miskin, lebih merupakan data penduduk di sekitar GK sementara.
Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret dan September. Susenas Maret termasuk kegiatan BPS yang cukup besar, respondennya mencapai sekitar 300.000 rumah tangga.
Selain susenas, BPS memanfaatkan pula hasil survei lainnya dalam menentukan GK. Salah satunya, Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD). SPPKD dipakai untuk memprakirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditas pokok.
Baca juga: Vasektomi untuk Miskin: Kebijakan yang Menyalahi Pancasila
Garis Kemiskinan berubah sesuai data Susenas waktu bersangkutan dan nilainya selalu meningkat. Terutama karena terjadinya inflasi pada “komoditas pengukur kemiskinan”, serta faktor perubahan pola konsumsi. Kecenderungan kenaikannya melampaui inflasi umum, atau bisa diartikan kenaikan harga bagi penduduk miskin lebih tinggi dibanding yang tidak miskin.
Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
GK nasional pada Maret 2024 sebesar Rp582.932 per kapita per bulan. Oleh karena secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia saat itu memiliki 4,78 orang anggota, maka GK per rumah tangga miskin sebesar Rp2.786.415 per bulan.
Ukuran GK rumah tangga ini sekurangnya bisa menjawab komentar nyinyir netizen tentang apakah bisa hidup dengan pengeluaran Rp20.000 per hari. Sebaiknya dibayangkan efisiensi pengeluaran unit keluarga dibanding individu, misalnya makanan dimasak sendiri atau tempat tinggal. Tentu sekitar Rp93.000 per keluarga pun belum memadai karenanya disebut miskin, namun masih masuk akal untuk bertahan hidup.
Aspek lain yang perlu diketahui adalah GK nasional bersifat hipotetis, bukan yang dipakai untuk menentukan jumlah penduduk miskin. GK yang dipakai untuk kondisi Agustus adalah GK propinsi dan berdasar wilayah domisili, yaitu kota atau desa. Sedangkan untuk kondisi Maret, GK kabupaten atau kota.
Perbedaan nilai GK antar wilayah cukup besar, bahkan dalam satu provinsi. Sebagai contoh GK yang tinggi adalah DKI Jakarta per September 2024 sebesar Rp846.085 per kapita per bulan. Sementara itu, GK Jawa Tengah sebesar Rp508.298 untuk perdesaan dan sebesar Rp532.913 untuk perkotaan.
Ukuran Bank Dunia
Bank Dunia memakai tiga ukuran untuk membandingkan kondisi berbagai negara, yaitu garis kemiskinan internasional, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah, dan garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas. Masing-masing sebesar US$2,15, US$3,65 dan US$6,85 per orang per hari, dalam kurs Purchasing Power Parity (PPP) tahun 2017.
Konsep PPP bermaksud mengatasi kesulitan terdapatnya harga barang dan jasa berbeda di antara berbagai negara. PPP atau paritas daya beli memungkinkan perbandingan nilai riil uang. Merupakan kurs dengan penyesuaian perbedaan biaya hidup dan tingkat harga masing-masing negara.
Bank Dunia juga mengakui bahwa perbandingan internasional estimasi kemiskinan melibatkan masalah konseptual dan praktis. Negara-negara memiliki definisi kemiskinan yang berbeda, dan perbandingan yang konsisten antarnegara bisa menjadi sulit. Konsep PPP dan garis kemiskinan berdasar kategori kelas negara merupakan salah satu upaya mengatasinya.
Publikasi Bank Dunia (Macro Poverty Outlook 2025) menyajikan perhitungan tingkat kemiskinan berbagai negara beserta proyeksinya hingga tahun 2027. Indonesia termasuk yang disajikan menurut tiga kategori, karena sudah masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas. Dalam ukuran kategori ini lah yang mencapai 60,03% pada 2024.
Dalam ukuran garis kemiskinan kelompok negara berpendapatan menengah bawah (US$3,65 PPP 2017 per orang per hari) sebesar 15,6%. Sedangkan dalam ukuran garis kemiskinan internasional (US$2,15) hanya sebesar 1,3%.
Baca juga: Ekonomi RI Sulit Tumbuh 5 Persen, Apalagi Menuju 8 Persen
Perlu diketahui data semacam ini telah lama disajikan Bank Dunia dalam open data di lamannya. Menjadi diskursus publik di Indonesia ketika media memberitakan berdasar laporan atau dokumen Macro Poverty Outlook 2025. Termasuk kesalahfahaman dalam mengkonversikan ukuran dolar dalam nilai rupiah.
Seperti yang telah dijelaskan di atas kurs PPP jauh berbeda dengan kurs transaksi atau pasar. Ada pula perbedaan antara PPP 2017 dengan 2011, atau sebelumnya terdapat PPP 2005. PPP dimaksud pun seolah kurs “tahun dasar” sehingga ada kurs tiap tahun berdasar itu bagi masing-masing negara.
Sayangnya, Bank Dunia sendiri tidak menyajikan sepenuhnya nilai kurs per tahun, terutama ketika terjadi perubahan “tahun dasar” PPP. Akibatnya ada berbagai penafsiran atau estimasi atas data dan proyeksi kemiskinan yang baru dipublikasi.
Sebagai contoh, bersumber dari CEIC data yang banyak dikutip, kurs 2017 PPP pada 2024 untuk Indonesia adalah Rp4.754,7 turun sedikit dari 2023 yang sebesar Rp4.821,6. Sementara itu, publikasi BPS yang menyebut kursnya sebesar Rp5.607,5 pada 2023.
Jika diterapkan kurs Rp4.754,7 pada ukuran garis kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah (US$3,65) maka setara Rp17.355 per orang per hari atau Rp520.670 per bulan. Batasnya lebih rendah dari GK BPS per Maret 2024 sebesar Rp582.923.
Baca juga:
Padahal, tingkat kemiskinan Indonesia menurut ukuran Bank Dunia ini sebesar 15,6% pada 2024. Lebih tinggi dari persentase penduduk miskin BPS yang sebesar 9,03% pada Maret 2024. Jika memakai perhitungan ini, seharusnya penduduk miskin versi BPS lebih banyak banyak dari Bank Dunia, karena batas garisnya lebih tinggi.
Kemungkinan yang lebih mendekati adalah kurs Rp5.607,5 pada 2023 yang diasumsikan tak berubah banyak pada 2024. Garis Kemiskinan Bank Dunia (US$3,65) setara dengan Rp20.467 atau Rp614.021 per bulan. Lebih tinggi dari GK BPS Maret 2024 yang sebesar Rp582.923.
Perlu diketahui pula bahwa Bank Dunia memakai data BPS untuk diolah, sebagaimana data negara lain yang bersumber dari negara masing-masing. Pemakaian contoh bulan Maret di atas juga karena memiliki sampel yang jauh lebih banyak dan survei yang lebih lengkap.
Sebagai penutup, penulis berpandangan ukuran Bank Dunia lebih berguna untuk perbandingan antar negara. Ukuran BPS tampak lebih menggambarkan kondisi Indonesia dan cukup berguna bagi dasar pengambilan kebijakan Pemerintah.
Tentu saja, ukuran BPS masih perlu diperbaiki dan kemungkinan memang perlu lebih tinggi dari saat ini. Akan tetapi perbaikannya bukan atas dasar “keriuhan”, melainkan evaluasi atau kajian atas hasil perhitungan selama ini. Perbaikan mencakup meta data, pelaksanaan survei, dan pengolahan data.
*) Ekonom Bright Institute
ADMIN