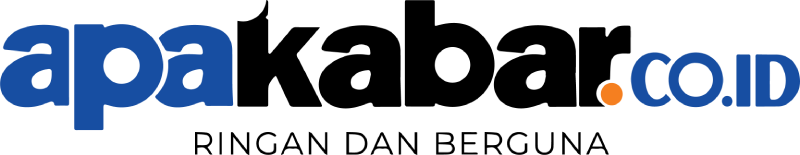Taman Nasional Meratus: Konservasi atau Ancaman bagi Masyarakat Adat?

apakabar.co.id, JAKARTA - Jika konservasi itu ibarat pesta besar demi menyelamatkan bumi, maka masyarakat adat adalah tamu lama yang justru sering disuruh duduk di pojok ruangan.
Itulah yang dirasakan masyarakat adat Dayak Meratus saat mendengar kabar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan kawasan Pegunungan Meratus seluas 119.000 hektare menjadi taman nasional.
Konflik konservasi negara dan masyarakat adat itu bukan cuma drama sinetron. Misalnya, di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah yang diresmikan pertama kali tahun 1982 dengan luasan 217.991,18 hektare, masyarakat adat Ngata Toro sudah ratusan tahun menjaga relasi dengan hutan berlandaskan kearifan lokal.
Tapi, ketika taman nasional ditetapkan, mereka malah sering dianggap “penjahat” karena aktivitas tradisional seperti bertani dan berburu dianggap ilegal oleh negara.
Data dari HuMa yang dilansir dari laman Mongabay (2024) mencatat, dari 86 konflik kehutanan di Indonesia, 27 terjadi di kawasan taman nasional, dengan 13 kasus melibatkan kriminalisasi masyarakat adat. Hutan lebih sering jadi arena konflik vertikal daripada taman anggrek liar.
Kasus serupa juga terjadi di kawasan Taman Nasional Kaeng Krachan, Thailand, yang ditetapkan pada tahun 1981 dan menjadi taman nasional terbesar di Thailand dengan total luasan 291.500 hektare juga punya sejarah konflik di mana masyarakat adat Karen mengalami pengusiran paksa.
Ini bukan cuma soal kehilangan tanah, tapi juga kehilangan identitas dan warisan budaya. Jadi, konservasi yang cuma fokus pada “hutan” tanpa memperhatikan “manusia” itu ibarat dengerin lagu-lagunya Bob Marley tanpa joget: kurang greget dan kurang yoman.
Kalau dilihat dari fakta sejarah taman nasional pertama di dunia yang ada di Amerika Serikat, yaitu Taman Nasional Yellowstone yang diresmikan pada 1 Maret 1872 juga erat konflik antara negara dengan masyarakat adat Native American.
Pemerintah Amerika Serikat menganggap kawasan Taman Nasional Yellowstone yang mencakup 3 negara bagian: Wyoming (bagian utama), Montana (di utara dan barat), dan Idaho (di barat) dengan total luas 899.116 hektare sebagai kawasan tidak berpenghuni dan menegasikan eksistensi suku-suku Native American yang sudah turun temurun mengelola alam di sana.
Demi menjaga “kealamian”, maka masyarakat adat di sana diusir secara paksa oleh pemerintah. Duh, pedih. Kini, Taman Nasional Yellowstone menerima jutaan pengunjung setiap tahunnya.
Malah jadi kasus overturisme! Dari data resmi National Park Service (NPS), hingga Oktober 2024, Taman Nasional Yellowstone telah menerima 4.692.810 kunjungan yang mengakibatkan degradasi ekologis seperti kemacetan, kerusakan habitat alami, konflik satwa-manusia, polusi dan sampah, erosi jalur alami dan kerusakan sumber air panas.
Dari Taman Nasional Yellowstone kita bisa paham bahwa konservasi ala negara memiliki kecenderungan tidak berpihak kepada masyarakat adat dan juga bisa bersifat tidak netral.
Ia bisa membentuk ulang relasi kuasa atas wilayah dan ruang hidup masyarakat. Taman Nasional Yellowstone adalah teladan awal konservasi modern, namun juga mengandung warisan kolonial, konflik agraria, dan eksklusi sosial yang masih relevan di berbagai negara termasuk Indonesia.
Nah, sekarang kita zoom ke Kalimantan Selatan, di mana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mengusulkan bagian dari bentang Pegunungan Meratus seluas 119.000 hektare yang mencakup 5 kabupaten (Banjar, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Kotabaru) jadi taman nasional.
Tujuannya terdengar mulia, melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga ekosistem. Tapi, dengerin juga suara buldoser yang ngebuka lahan ugal-ugalan di lerengan Meratus!” Masyarakat Adat Dayak Meratus khawatir kalau taman nasional ditetapkan tanpa partisipasi mereka dalam prosesnya, mereka bakal di-ghosting dari tanah leluhur mereka sendiri.
Padahal, Masyarakat Dayak Meratus sudah dari dulu sepeduli itu sama alam, mereka tidak cuman bahas soal teori atau bicara usulan; mereka sudah dari dulu menghidupi konservasi, bahkan sudah sampai tahap relasi spiritual.
Apa buktinya? Ya, dengan adanya hutan-hutan keramat yang gak boleh dieksploitasi, perladangan gilir balik, gunung yang jadi tempat ritual peribadatan yang gak bisa sembarang orang masuk ke sana.
Ya, itu bentuk konservasi ala mereka. Singkatnya, pengetahuan masyarakat adat Meratus memang sudah dari sono-nya punya ikatan sama alam.
WALHI Kalimantan Selatan pada tahun 2021 mengidentifikasi sedikitnya ada 14 wilayah adat yang tersebar di Pegunungan Meratus dan rawa gambut di Kalimantan Selatan dengan total luas wilayah 220.000 hektare yang dikelola oleh 171 komunitas adat di 9 kabupaten di Kalimantan Selatan.
Ancaman sebenarnya adalah korporasi industri ekstraktif yang memanfaatkan sumber daya alam secara ugal-ugalan. WALHI Kalimantan Selatan pada tahun 2024 menghimpun data bahwa 51,57% wilayah Kalimantan Selatan sudah dibebani izin konsesi perusahaan.
Menjadikan kawasan Meratus sebagai taman nasional yang eksklusif bagi manusia adalah bentuk tindak laku negara mempersempit ruang hidup masyarakat, khususnya masyarakat adat.
Ditambah lagi, keberadaan dan hak-hak masyarakat adat belum diakui dan belum terlindungi penuh karena macetnya RUU Masyarakat Adat juga Perda-perda serupa yang sifatnya seakan-akan sekadar formalitas jadi hal vital lagi fundamental sebelum membahas soal kewilayahan.
Lagipula, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 sudah jelas bilang bahwa “hutan adat berada di wilayah adat dan bukan hutan negara.”
Meresmikan 364.501 hektare Geopark Meratus yang punya situs pemandangan kapal tongkang batu bara di bawah Jembatan Barito, Alalak, Barito Kuala (jujurly seleranya freak betul.
Cek situs nomor 9 di laman resmi Geopark Meratus) sampai mengusulkan taman nasional cepatnya bagai kijang berlari, tapi mengakui hutan adat lambatnya kaya siput.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan menyatakan bahwa potensi luasan hutan adat di Kalimantan Selatan yaitu 66.347 hektare di 7 kabupaten.
AMAN Kalimantan Selatan juga menyerahkan peta wilayah adat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan total 53 peta yang berluaskan 265.390 hektare.
Sayangnya, belum satupun hutan adat di Kalimantan Selatan memiliki SK Penetapan Hutan Adat.
Kalau bisa berandai-andai punya kemampuan mendengar suara pohon, pasti kanopi hijau Meratus berbisik, “Jangan biarkan kami jadi saksi bisu pengusiran tanpa alasan.”
Masyarakat adat adalah akar yang menancap kuat, tiada henti menopang kehidupan hutan. Kalau akar ini dicabut, jangan heran kalau pohon-pohon pun goyah dan tumbang.
Persimpangan jalan antara konservasi dan keadilan ekologi adalah tantangan besar yang harus diselesaikan dengan hati dan kepala dingin, namun tetap kritis.
Negara bisa dikatakan berhasil melindungi kelestarian alam jika mampu mengakui dan menyerahkan pengelolaan wilayah adat kepada yang berhak, yaitu masyarakat adat. Jadi, negara yang condong pada kapitalisme gak perlu sotoy bertingkah “si paling paham konservasi”.
Tinggal lihat dinamika ke depan, negara memihak yang mana? Hati nurani dan keadilan atau konservasi semu yang memarginalisasi dan buta terhadap ancaman korporasi.
ADMIN