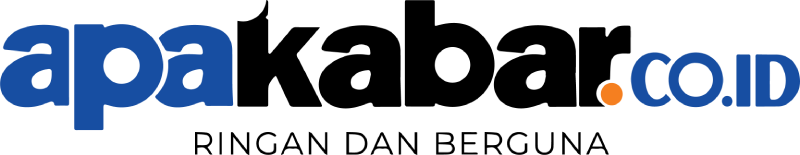Inspirasi 'Made in China' 2025 untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045
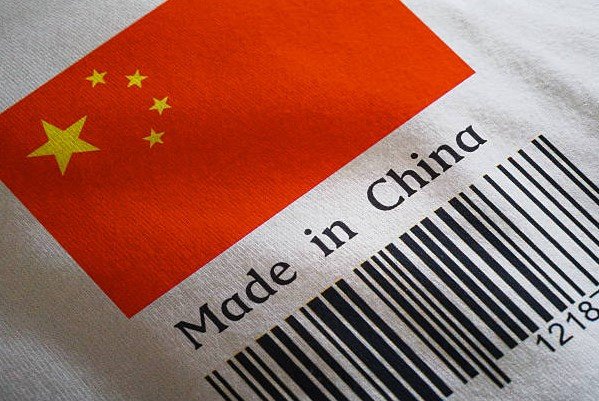
Oleh: Antonius Sumarwan*
Tiga kata sederhana --Made in China-- dulu identik dengan produk murah, seperti mainan plastik, tekstil, atau barang rumah tangga. Kini, kata itu melekat pada mobil listrik, robot humanoid, drone, hingga pabrik cerdas.
Transformasi citra itu tidak terjadi secara kebetulan. Ia merupakan buah dari kebijakan industri besar yang dicanangkan Beijing, satu dekade lalu: Made in China 2025.
Diluncurkan tahun 2015 oleh Perdana Menteri Li Keqiang, rencana ini menargetkan modernisasi 10 sektor strategis, mulai dari kecerdasan buatan, robotika, energi terbarukan, hingga dirgantara. Tujuannya jelas: membawa China keluar dari stigma sebagai “pabrik dunia” dan menempatkannya sebagai pemimpin inovasi global.
Hasilnya, kini nyata. BYD telah melampaui Tesla sebagai penjual mobil listrik terbesar di dunia. Kapal buatan galangan Tiongkok mengalahkan gabungan Jepang dan Korea Selatan. Xiaomi mengoperasikan pabrik mobil listrik dengan 700 robot yang mampu menghasilkan satu mobil setiap 76 detik. Dan jalur kereta cepat sepanjang 45.000 km menjadikan Tiongkok pemilik jaringan rel tercepat terbesar di dunia.
Banyak orang mengira Made in China 2025 adalah akhir dari perjalanan industri China. Padahal, itu hanyalah tahap awal dari visi besar jangka panjang yang dicanangkan Beijing. Peta jalannya dibagi dalam tiga fase strategis.
Fase pertama berlangsung hingga tahun 2025, dengan misi utama mengejar ketertinggalan di sektor-sektor kunci. Fokusnya adalah membangun fondasi: memperkuat industri dasar, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan Tiongkok mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam teknologi penting.
Memasuki tahun 2035, ambisinya meningkat. China menargetkan diri untuk berdiri sejajar dengan para pemimpin industri dunia. Pada tahap ini, bukan hanya soal mengejar, tetapi juga menyamai standar kualitas, teknologi, dan daya saing global. Mereka ingin produk-produk “Made in China” tidak lagi dipandang sebagai murah meriah, melainkan sebagai simbol kualitas dan inovasi.
Baca juga: Jalan Tengah Kontroversi Satu Akun Medsos Per Orang
Puncaknya akan tiba pada 2049, tepat seratus tahun berdirinya Republik Rakyat China. Saat itulah mereka bertekad untuk menjadi pemimpin global manufaktur dan inovasi. Visi ini bukan sekadar ekonomi; ia sarat makna simbolis, sebuah deklarasi bahwa China yang dulu dikenal sebagai “pabrik dunia” dengan upah murah telah bertransformasi menjadi pusat inovasi dan kekuatan industri paling berpengaruh di planet ini.
Keberanian visi ini juga memantik resistensi. Amerika Serikat menilai rencana itu sebagai ancaman langsung. Pemerintahan Donald Trump melancarkan perang dagang, memberlakukan tarif tinggi, serta menjatuhkan sanksi kepada perusahaan teknologi Tiongkok. Presiden Joe Biden melanjutkan dengan larangan ekspor chip canggih.
Karena itu, perjalanan menuju target besar itu tidak selalu lancar. Setelah perang dagang dengan Amerika Serikat memanas, istilah Made in China 2025 perlahan menghilang dari dokumen resmi Beijing. Bukan berarti strateginya berhenti, sebaliknya, pemerintah China hanya berusaha menghindari gesekan geopolitik yang makin tajam.
Nama boleh berubah, kadang diganti dengan istilah, seperti dual circulation (tidak hanya mengandalkan ekspor, melainkan juga menggarap pasar dalam negeri) atau kemandirian dalam sains dan teknologi, tetapi substansinya tetap dijalankan secara konsisten. Di balik layar, mesin transformasi industri China terus bergerak, bahkan dengan akselerasi yang lebih tenang, namun terarah.
Alih-alih melemah, tekanan eksternal justru memperkuat tekad China untuk membangun rantai pasok mandiri. Seorang pengamat menyebut, “Perang dagang tidak membunuh rencana itu. Justru mempertebal determinasi China membangun kapasitasnya sendiri.”
Relevansi untuk Indonesia
Kisah transformasi lewat Made in China 2025 memberi cermin berharga bagi Indonesia yang tengah menapaki jalan panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Sama seperti China yang berani merancang peta jalan industrialisasi jangka panjang, Indonesia pun telah menyiapkan empat tahap transformasi ekonomi. Hal ini telah ditetapkan dalam UU No. 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025 - 2045 yang harus menjadi acuan semua presiden dan pemimpin daerah dalam penyusunan program pembangunan jangka menengah.
Tahap pertama (2025–2029): penguatan transformasi. Di sini fokus utama ada pada hilirisasi sumber daya alam, riset, inovasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pengalaman China mengajarkan bahwa hilirisasi tidak bisa berhenti pada sekadar membangun smelter. Hilirisasi hanya akan berbuah sukses bila disertai investasi besar pada riset, teknologi, dan mesin produksi lokal. Artinya, Indonesia tidak boleh puas hanya mengekspor nikel, tetapi harus menguasai teknologi baterai, hingga mobil listrik yang berbasis nikel.
Baca juga: Tax Amnesty di Prolegnas 2025: Untuk Siapa RUU Ini Dibuat?
Tahap kedua (2030–2034): Akselerasi Transformasi. Target fase ini adalah lonjakan produktivitas secara masif dan penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok menunjukkan bahwa percepatan semacam ini mustahil tanpa ekosistem industri yang matang. Pemerintah Indonesia harus lebih dari sekadar memberi subsidi; ia perlu menciptakan lingkungan bisnis kondusif, dengan insentif tepat, infrastruktur andal, dan regulasi yang mendorong perusahaan berinovasi.
Tahap ketiga (2035–2039): Ekspansi Global. Di titik ini, Indonesia bercita-cita menjadi kekuatan ekonomi regional yang terhubung dalam rantai pasok global dengan ekspor yang kokoh. Tiongkok memberi contoh konkret: ketika pasar Barat menutup diri, mereka menembus pasar Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin.
Diversifikasi pasar dan kemampuan masuk dalam rantai pasok global akan sangat menentukan daya tahan ekonomi Indonesia. Keikusertaan Indonesia sebagai anggota BRICS merupakan langkah tepat untuk memperluas pasar ini.
Tahap keempat (2040–2045): Indonesia Emas. Visi akhirnya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi. Sementara Tiongkok menargetkan diri sebagai pemimpin inovasi dunia pada 2049, Indonesia juga harus menyiapkan diri agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta teknologi. Kuncinya ada pada kualitas sumber daya manusia dan keberanian berinvestasi di riset frontier,mulai dari kecerdasan buatan, bioteknologi, hingga energi bersih.
Dengan demikian, peta jalan Indonesia Emas 2045 bisa dipandang sebagai “Made in Indonesia” versi kita sendiri, sebuah transformasi yang menuntut visi panjang, komitmen politik yang konsisten, serta keberanian mengambil risiko pada bidang yang akan menentukan masa depan.
Peluang dan Tantangan
Seperti China, Indonesia menghadapi tantangan eksternal: persaingan geopolitik, risiko perang dagang, dan tuduhan praktik industri yang merusak lingkungan. Hanya saja, Tiongkok juga mengajarkan bahwa tekanan global bisa menjadi katalis untuk memperkuat kemandirian.
Kunci keberhasilan Indonesia terletak pada konsistensi kebijakan lintas pemerintahan. Hal ini sebenarnya sudah ditegaskan dalam UU No 59 Tahun 2024 RPJP Nasional yang menjadi arah pembangunan bangsa selama 20 tahun. Sayangnya, dalam praktiknya, setiap pergantian pemerintahan sering kali diwarnai dengan perubahan prioritas yang bersifat jangka pendek dan politis.
Akibatnya, kesinambungan program industri, riset, maupun inovasi kerap terputus di tengah jalan. Konsistensi lintas pemerintahan berarti setiap rezim politik wajib menurunkan visi RPJP ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), tanpa mengorbankan orientasi jangka panjang. Dengan demikian, industrialisasi dan penguasaan teknologi benar-benar menjadi prioritas nasional yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek politik lima tahunan.
Baca juga: Didukung PBB, KKP Bakal Kembangkan Industri Rumput Laut
Dengan bonus demografi yang dimiliki, Indonesia punya peluang besar. Tetapi tanpa investasi serius pada riset, inovasi, dan pendidikan vokasi, hilirisasi hanya akan berhenti pada ekspor bahan setengah jadi.
Selain itu, secara internal Indonesia perlu melakukan transformasi birokrasi untuk membangun iklim investasi yang ramah bagi investor. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan sistem birokrasi satu pintu yang transparan untuk memotong rantai pungutan liar, pemberian insentif pajak bagi industri yang menciptakan efek berganda pada perekonomian, percepatan perizinan berbasis digital, serta penyelarasan regulasi pusat dan daerah agar tidak saling bertabrakan.
Made in China 2025 menunjukkan bahwa sebuah negara bisa mengubah reputasinya dalam satu dekade dengan visi yang jelas, eksekusi konsisten, dan keberanian menghadapi tekanan global.
Indonesia kini berada di titik yang sama: memulai perjalanan menuju 2045. Jika mampu mengambil pelajaran dari China, mengombinasikan hilirisasi dengan inovasi, memperkuat produktivitas tenaga kerja, dan membangun ekosistem industri berdaya saing, maka cita-cita Indonesia Emas bukanlah utopia. Ia bisa dan harus menjadi kenyataan.
*) Dosen magister manajemen Universitas Sanata Dharma, peneliti di Global Development Research Center (GDRC) dan Indonesia China Parentship Studies (INCHIPS)
ADMIN