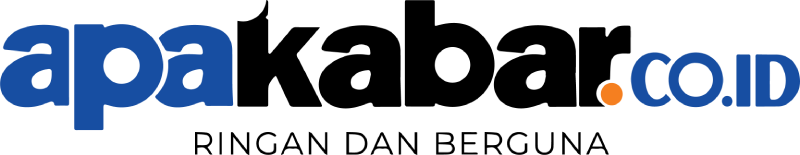OPINI
Ancaman Krisis Ekonomi Dunia: Ketika 'Bubble AI' Siap Meledak
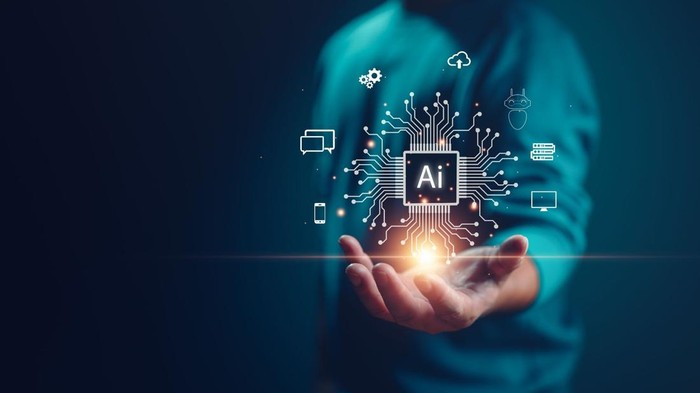
Oleh Achmad Nur Hidayat*
Apakah kecerdasan buatan (AI) benar-benar mesin kemakmuran baru—atau bom waktu yang sedang dirakit bersama?
Pertanyaan ini wajar ketika pertumbuhan Amerika Serikat pada 2025 disebut sangat bergantung pada belanja AI, angkanya sekitar 40% pertumbuhan PDB tahun 2025 ini, dan pada satu kuartal terakhir bahkan mendekati 90%.
Di tengah euforia itu, kita melihat perusahaan berlomba mendirikan kampus komputasi multi-gigawatt yang disebut-sebut “mendekati seluas Manhattan.” Apakah ini tanda kebangkitan produktivitas, atau sinyal awal gelembung? Apakah ini fondasi produktivitas baru, atau sinyal awal gelembung?
Ekspektasi yang Menyalip Nilai Riil
Masalah inti AI hari ini bukan pada inovasinya, melainkan ketimpangan antara ekspektasi finansial dan nilai riil.
Belanja untuk pusat data, chip, dan infrastruktur melonjak triliunan, sementara pendapatan yang benar-benar terealisasi baru puluhan miliar.
Ketika kapital mengalir lebih cepat daripada kemampuan pasar mencerna produk, risiko koreksi pasar menguat.
Kita pernah melihat pola serupa pada dot-com bubble: narasi masa depan yang memukau mendorong valuasi jauh menyalip kinerja.
Jika AI menjadi satu-satunya tonggak pertumbuhan agregat, ekonomi akan terpapar volatilitas siklus investasi—begitu ekspektasi laba meleset, penundaan proyek menyebar, permintaan chip melemah, dan rantai pemasok ikut tersengal.
Katedral dengan Bangku Kosong
Bayangkan sebuah katedral megah dibangun dalam tempo singkat. Menara menjulang, kubah berlapis emas, tetapi bangku jemaat belum terisi.
Industri AI ibarat katedral itu: ambisi arsitekturalnya mengagumkan, tetapi “persembahan” dari jemaat—yakni arus kas—belum mengimbangi biaya marmer dan kaca patri.
Seindah apa pun bangunannya, pondasi kas yang rapuh membuatnya mudah retak ketika getaran kecil datang.
Euforia, Energi, dan Ekonomi Politik Data
Skala investasi AI menembus nalar. McKinsey memperkirakan kebutuhan belanja pusat data global jelang 2030 mendekati US$6,7 triliun—sebuah lomba membangun infrastruktur komputasi terbesar dalam sejarah industri.
Namun, pendapatan riil layanan AI yang masih “puluhan miliar” menandakan neraca yang timpang: triliun rupiah dibakar untuk mengejar pasar yang belum terbukti elastis. Ketika neraca tidak klop, risiko koreksi pasar membesar.
Euforia AI mudah menggeser rasionalitas menjadi semacam ideologi teknologi. Perusahaan membentangkan janji “mesin serba bisa” sambil menyedot listrik dan data publik dalam skala belum pernah terjadi.
Beban energinya nyata: pusat data memerlukan pasokan stabil berkapasitas besar, yang dalam praktiknya masih kerap ditopang bahan bakar fosil. Paradoks pun muncul: industri yang menjanjikan masa depan hijau justru menambah jejak emisi hari ini.
Di atas itu, ekonomi politik data menimbulkan persoalan keadilan. Konten publik—tulisan, gambar, suara—ditambang untuk melatih model yang kemudian dijual kembali ke masyarakat.
Jika izin, kompensasi, dan keamanan data tertinggal dari laju komputasi, yang terjadi adalah kolonialisme digital: kuasa pengetahuan dan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir perusahaan.
Pro-Inovasi, Pro-Akal Sehat
Mendeteksi gelembung bukan berarti anti-inovasi. Seperti bandara yang sibuk, kita tidak mematikan mesin pesawat; kita memperkuat menara kontrol, memasang radar, dan mengatur koridor. AI pun demikian. Yang kita butuhkan adalah kualitas pertumbuhan, bukan sekadar kecepatannya.
Pertanyaan kebijakannya sederhana: apakah belanja AI benar-benar menaikkan produktivitas menyeluruh—di pabrik, sawah, rumah sakit, sekolah—atau hanya memindahkan laba sambil membebani jaringan listrik dan konsumen?
Gagasan Kebijakan: Empat Rem yang Menjaga Laju
Pertama, transparansi emisi digital dan energi bersih. Tetapkan standar porsi energi terbarukan minimum bagi pusat data berdaya besar, lengkap dengan pelaporan karbon granular per satuan komputasi dan kewajiban efisiensi pendinginan. Tanpa itu, ekspansi server hanyalah memindahkan emisi dari pabrik ke layar.
Kedua, uji tekanan makro-keuangan. Perlakukan kampus AI sebagai proyek infrastruktur berisiko teknologi tinggi: uji sensitivitas pendapatan, harga listrik, biaya modal, dan skenario “pendapatan tertunda”. Regulator keuangan harus memastikan pembiayaan AI tidak menular menjadi gelembung kredit konstruksi dan utilitas.
Ketiga, tata kelola data dan persaingan yang adil. Perjelas hak cipta dan izin data, tegakkan kompensasi bagi kreator, dan dorong audit algoritma untuk model berdampak luas. Cegah konsolidasi berlebihan di pasar cloud dan komputasi dengan kebijakan antimonopoli yang menjaga ruang inovasi startup.
Keempat, insentif berbasis hasil. Prioritaskan dukungan fiskal pada solusi AI yang terbukti memangkas biaya publik, menekan emisi, atau meningkatkan mutu layanan dasar. Dengan begitu, setiap rupiah insentif “membeli” produktivitas, bukan sekadar kapasitas komputasi.
Menarik Garis ke Indonesia: Peluang Tanpa Terjebak Euforia
Indonesia tak perlu menyalin “Manhattan digital”. Fokuskan pada AI hemat sumber daya (frugal AI) yang menyelesaikan masalah nyata: prediksi gagal panen, efisiensi logistik, deteksi kecurangan bansos, optimasi konsumsi listrik daerah.
Pusat data boleh datang—namun syarat energi bersih, efisiensi, dan integrasi ke target bauran EBT harus tegas.
Di pembiayaan, gunakan skema proyek-linked productivity: insentif cair setelah manfaat terukur hadir di lapangan, bukan di presentasi.
Menjaga Akal Sehat di Tengah Sorak Sorai
Gelembung adalah drama lama dengan kostum baru. Tugas kebijakan publik bukan mematikan musik, melainkan memastikan pangggungnya kokoh: listriknya bersih, datanya adil, pasarnya kompetitif, pembiayaannya berhitung.
Bila itu dilakukan, AI tetap menjadi alat pemerdekaan—bukan alat pemusatan kuasa dan emisi.
Kita boleh terpukau pada menara komputasi yang menjulang, tetapi yang menyelamatkan perekonomian bukan kubahnya, melainkan fondasinya. Teknologi tanpa kebijaksanaan hanyalah algoritma menuju kehancuran.
*) Ekonom & Pakar Kebijakan Publik, UPN Veteran Jakarta
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY