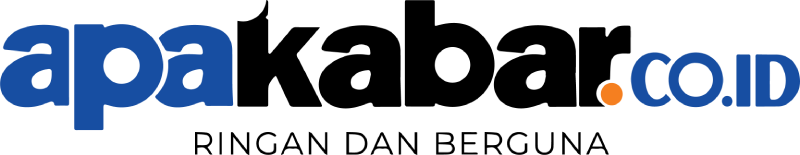OPINI
Membina Generasi Alpha di Era Layar

Oleh: Pormadi Simbolon*
Anak-anak yang lahir pada dekade terakhir ini, disebut Generasi Alpha, tumbuh di dunia yang sejak awal sudah digital. Sejak usia dua tahun, banyak dari mereka sudah akrab dengan layar, dari video YouTube, gim edukatif, hingga aplikasi belajar interaktif.
Buku bergambar dan dongeng klasik perlahan tergeser oleh video animasi dengan warna mencolok dan lagu yang mudah diingat.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah cermin zaman. Dalam masyarakat yang serba cepat dan visual, perhatian menjadi mata uang baru. Anak-anak pun belajar untuk berpikir dalam gambar dan suara, bukan dalam teks panjang.
Istilah Generasi Alpha pertama kali diperkenalkan oleh demograf asal Australia, Mark McCrindle, untuk menyebut anak-anak yang lahir mulai tahun 2010 hingga sekitar 2025, generasi pertama yang sejak awal hidup dalam dunia gawai, media sosial, dan kecerdasan buatan.
Beberapa lembaga riset seperti Pew Research Center memang menempatkan tahun 2012 sebagai batas akhir Generasi Z, namun dalam konteks perilaku dan budaya digital, anak-anak kelahiran 2010–2012 lebih dekat dengan karakter Gen Alpha: visual, cepat beradaptasi dengan teknologi, dan terbiasa belajar melalui layar.
Karena itu, anak kelahiran 2012 pun dapat dikatakan bagian dari generasi digital murni yang sedang tumbuh di sekitar kita.
Sebuah riset dari Morning Consult (2024) menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak Gen Alpha menonton video setiap hari, sementara aktivitas membaca buku menempati posisi jauh di bawah.
Penelitian serupa di Indonesia, misalnya oleh Dwi Putri dan Nurhaliza (2023) dari Universitas PGRI Palembang, menegaskan bahwa lingkungan digital yang dominan telah mengubah cara anak belajar, berinteraksi, dan membangun makna.
Namun di balik kemudahan dan kecepatan itu, ada persoalan mendalam. Anak-anak kini lebih mudah terpesona, tetapi lebih sulit fokus; cepat memahami permukaan, tetapi sering kehilangan kedalaman.
Kita sedang menyaksikan lahirnya generasi yang tumbuh dengan kemampuan digital tinggi, tetapi rentan kehilangan keheningan batin yang diperlukan untuk berpikir mendalam dan berelasi secara manusiawi.
Dari Larangan ke Pendampingan
Reaksi spontan banyak orang tua adalah membatasi atau melarang anak menatap layar. Namun, larangan total sering berakhir dengan konflik, bahkan justru menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih besar. Kita perlu bergeser dari strategi pengendalian menuju strategi pendampingan.
Pendampingan berarti orang tua hadir, bukan sekadar mengawasi. Mereka menjadi "kurator" dunia digital anak --memilihkan tontonan yang mendidik, menonton bersama, dan mengajak anak berdialog tentang nilai-nilai di balik layar. Anak perlu diajak mengenali perbedaan antara hiburan dan pembelajaran, antara kesenangan sesaat dan pengetahuan yang bermakna.
Peran orang tua di era digital bukan lagi sekadar pelindung, tetapi penuntun nilai. Dalam dunia yang banjir informasi, anak tidak butuh lebih banyak data, melainkan lebih banyak makna. Pendampingan yang penuh kasih sayang menjadi fondasi untuk menumbuhkan kebijaksanaan digital.
Keluarga, dengan demikian menjadi sekolah pertama literasi digital. Orang tua yang bijak bukan yang menolak teknologi, tetapi yang menuntun anak menggunakan teknologi untuk menemukan makna.
Misalnya, ketika anak menonton YouTube, orang tua tidak hanya membatasi waktu, tetapi menonton bersama dan berdialog tentang isi tontonan: "Menurutmu, tokoh itu berbuat baik atau tidak?" atau "Kalau kamu di posisinya, apa yang akan kamu lakukan?"
Saat anak menggunakan gawai, orang tua bisa mengarahkan pencarian ke hal-hal yang membangkitkan rasa ingin tahu, seperti menonton video tentang ulat yang berubah menjadi kupu-kupu, lalu bersama-sama mencarinya di taman.
Dengan cara sederhana ini, teknologi berubah dari alat hiburan menjadi sarana belajar dan relasi. Anak belajar berpikir kritis, sekaligus merasakan kehangatan kebersamaan.
Menumbuhkan Budaya Baca
Kemajuan digital memang mengubah cara anak berinteraksi dengan teks, tetapi tidak berarti mereka harus kehilangan budaya membaca. Justru di era layar, membaca perlu dihadirkan dengan cara baru, melalui buku digital bergambar, cerita interaktif, dan kebiasaan membaca bersama.
Kebiasaan sederhana seperti membacakan cerita sebelum tidur bukan sekadar memperkaya kosa kata, melainkan juga memperdalam hubungan emosional antara anak dan orang tua. Di ruang itu, anak belajar empati, imajinasi, dan nilai-nilai hidup yang tidak bisa diajarkan oleh algoritma.
Sebuah penelitian oleh Astuti dan Handayani (2024) menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dan keterikatan emosional dengan ibu memiliki pengaruh signifikan terhadap minat baca anak. Anak-anak yang tumbuh dalam rumah dengan tradisi membaca cenderung memiliki rasa ingin tahu lebih besar dan kemampuan bahasa yang lebih baik.
Sekolah pun tidak boleh tinggal diam. Literasi di sekolah tidak cukup berhenti pada kemampuan teknis membaca dan menulis, melainkan perlu menghidupkan literasi makna --kemampuan menafsirkan dunia, memahami nilai, dan membedakan yang baik dari yang menyesatkan.
Pembelajaran di ruang kelas seharusnya tidak hanya mengajarkan anak memahami isi teks, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas sosial dan moral di sekitarnya.
Dari Konsumen ke Pembelajar
Generasi Alpha tidak dapat dilepaskan dari teknologi. Namun, teknologi tidak boleh menjadikan mereka sekadar konsumen pasif konten, melainkan pembelajar aktif yang kreatif. Di sinilah pentingnya pembinaan yang menyeimbangkan antara kemampuan digital dan kedalaman nilai kemanusiaan.
Guru dan orang tua perlu menanamkan tiga sikap dasar: kritis, kreatif, dan berbelarasa. Kritis agar anak tidak mudah terpengaruh arus informasi; kreatif agar mampu menggunakan teknologi untuk berkarya; dan berbelarasa agar tidak kehilangan sisi kemanusiaannya di tengah dunia virtual.
Zygmunt Bauman pernah mengingatkan bahwa kita hidup dalam masyarakat cair—segala sesuatu bergerak cepat dan berubah tanpa henti. Dalam dunia seperti itu, tugas pendidikan bukan lagi sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan membentuk karakter yang tahan dalam arus. Anak-anak perlu dibekali kemampuan reflektif agar tidak tenggelam dalam derasnya perubahan dan mampu menata arah hidupnya sendiri.
Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menumbuhkan keseimbangan antara teknologi dan kebijaksanaan, antara kemampuan berpikir dan kemampuan merasakan. Dunia digital memberi peluang luas bagi kreativitas, tetapi tanpa fondasi nilai, kreativitas mudah berubah menjadi kekacauan.
Generasi Alpha adalah cermin dari dunia yang kita ciptakan. Jika mereka tampak gelisah, cepat bosan, dan sulit fokus, itu mungkin karena dunia orang dewasa juga semakin tergesa-gesa dan kehilangan ruang hening. Maka membina mereka berarti juga membenahi diri kita sendiri—menciptakan rumah, sekolah, dan masyarakat yang memberi waktu untuk mendengarkan, membaca, dan merasakan.
Oleh karena itu, kita tidak bisa menghentikan arus digital, tetapi kita bisa menuntun arah. Dengan pendampingan yang bijak, budaya baca yang hidup, dan pendidikan yang menumbuhkan makna, generasi layar ini bisa tumbuh menjadi generasi terang yang cerdas secara digital, mendalam secara manusiawi, dan berakar dalam nilai kebaikan.
*) Pegiat literasi, pemerhati isu pendidikan dan kebudayaan
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY