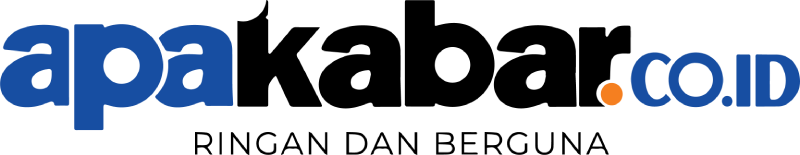OPINI
Urgensi Membangun Ekosistem Data Pangan Terintegrasi

Oleh: J. Widodo, R Shofiyati L. Gandharum, H. Sadmono, AS*
Fragmentasi data pangan masih menjadi persoalan bagi Bangsa Indonesia, sehingga seringkali keputusan pemerintah di sektor pangan dipersoalkan publik.
Fragmentasi data, sebetulnya bukan hanya ciri khas di sektor pangan, tetapi juga di berbagai sektor, meskipun kebijakan satu peta telah digaungkan di setiap sektor, dengan instansi yang ditunjuk sebagai wali data.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia juga telah diterbitkan dan mulai berlaku 17 Juni 2019 sebagai upaya standardisasi dan integrasi data lintas sektor.
Dengan luas lahan sawah mencapai sekitar 7,46 juta hektare dan lahan kering lebih dari 144,5 juta hektare yang tersebar di berbagai kondisi agroekosistem, kebutuhan akan data yang terpadu, akurat, dan mudah diakses menjadi semakin mendesak.
Kini di era informasi teknologi yang semakin maju dan dinamis, Indonesia membutuhkan kebijakan yang melampaui kebijakan satu peta.
Di era digital peta telah bertransformasi menjadi geo informasi spasial yang bukan hanya sekadar peta, tetapi lapisan-lapisan data raksasa yang memiliki atribut berupa lokasi berkoordinat.
Dampaknya, kebijakan satu peta tak lagi memadai karena Indonesia membutuhkan satu ekosistem data yang terhubung. Setiap instansi pemerintah boleh saja memiliki data spasial masing-masing, tetapi saling terkoneksi dalam sebuah geoportal hub collection.
Ilustrasinya kurang lebih seperti di dunia ini terdapat berbagai data, satelit seperti Landsat, Sentinel, ALOS PALSAR, maupun MODIS, tetapi dapat diakses dari satu platform.
Setiap pengguna memahami bahwa setiap data satelit tentu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, tergantung resolusi spasial, temporal, dan radiometriknya.
Setiap keunggulan di satu produk digunakan untuk menutupi kelemahan pada produk lainnya, demikian juga sebaliknya, sehingga informasi yang diperoleh semakin utuh.
Data Pangan
Pada kasus data pangan, tentu Indonesia membutuhkan data yang valid, tetapi perlu juga disadari bahwa setiap data yang dikeluarkan oleh sebuah instansi memiliki level akurasi masing-masing.
Kesediaan memublikasikan tingkat akurasi di setiap lokasi sebagai bagian dari metadata menjadi hal penting pada ekosistem data yang saling terhubung.
Data dari instansi berbeda dapat menjadi alat untuk kalibrasi agar data yang dihasilkan tidak overestimate atau sebaliknya underestimate.
Saat ini satu-satunya data yang digunakan untuk pengambilan kebijakan pertanian adalah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi tentunya Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) maupun Kementerian Pertanian (Kementan) juga menghasilkan data yang disesuaikan dengan kebutuhan kedua institusi tersebut.
Perbedaan ketiga data tersebut bukan untuk diperdebatkan karena sumber data yang sama diolah dengan definisi dan metodologi yang berbeda juga tentu hasilnya berbeda. Apalagi jika sumber data yang digunakan memang berbeda, sehingga perbedaan hasil merupakan sebuah keniscayaan.
Dengan sistem penjaminan mutu berlapis yang disebut quality gates, model ini memastikan akurasi minimal 80 persen dan deviasi estimasi tidak lebih dari 5 persen terhadap data resmi.
Lebih dari itu, mixed method produk BPS gabungan data kerangka sampel area (KSA) dan data satelit juga membuka peluang besar menuju real-time crop monitoring, sesuatu yang dulu hanya bisa diimpikan. BRIN dan BPS sebenarnya sedang memperlihatkan satu hal penting bahwa pangan tidak bisa dilepaskan dari geospasial.
Di sisi lain, Bappenas juga telah menegaskan pentingnya data spasial untuk perencanaan pangan jangka panjang.
Melalui platform Indonesia Data Management for Agricultural Information (IDMAI) yang dapat diakses di pangan.bappenas.go.id, perencana dapat memantau selain prediksi luas panen juga memantau alih fungsi lahan pertanian, dan kebutuhan irigasi berbasis data geotagging.
Dengan dukungan proyeksi dan skenario berbasis kecerdasan buatan (AI), perencanaan pembangunan kini lebih dari sekadar membaca tren masa lalu, tetapi juga menyiapkan masa depan yang terukur.
Kementerian Pertanian juga telah memiliki website data pangan. Pada kasus demikian, tantangan utama bangsa ini adalah mengolaborasikan fragmentasi data dengan Geoportal hub connection.
Di sinilah geospatial intelligence berperan, yakni kemampuan mengubah data spasial menjadi wawasan (insight) untuk pengambilan keputusan.
Demikian pula subsektor pangan yang lain, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tentu memiliki dan menunjukkan bagaimana geoinformatika bisa diterapkan untuk pangan biru.
Data spasial dari 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) menunjukkan status stok ikan pelagis besar dan kecil, dengan warna-warna yang menandai zona aman, hati-hati, atau kritis.
Sistem ini menjadi dasar penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, program unggulan KKP untuk menjaga keberlanjutan laut Indonesia.
Ekonomi Biru
Dengan produksi ikan dan rumput laut pada kisaran 20–25 juta ton per tahun, Indonesia memiliki potensi besar sebagai lumbung protein dunia.
Dengan luas wilayah laut mencapai lebih dari 6,4 juta kilometer persegi yang menyimpan sumber daya pangan hayati dan nonhayati yang berlimpah, potensi ekonomi biru Indonesia seharusnya dapat dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan global.
Tekanan aktivitas manusia, penurunan kawasan konservasi, dan perubahan iklim mengancam keseimbangan ekosistem laut. Tanpa sistem pemantauan spasial yang kuat, overfishing dan degradasi laut bisa menjadi bumerang jangka panjang bagi ketahanan pangan nasional.
Ketika ekosistem data pangan baru terwujud, maka ketahanan pangan di masa depan tidak hanya bergantung pada seberapa luas sawah dan laut yang dimiliki, tetapi seberapa cerdas membaca data spasial.
GeoMIMO dapat menjadi Geoportal connection hub yang menjadi ekosistem data geospasial, sekaligus sumber data pendukung bagi mixed method dan IDMAI yang diproduksi berbagai lembaga pemerintah. Hal ini menjadi contoh nyata ilmu geoinformatika dapat menjembatani data, kebijakan, dan keberlanjutan.
Meskipun demikian, jalan menuju integrasi nasional masih panjang. Masih ada kendala akses internet di daerah, keterbatasan SDM teknis, hingga biaya lisensi perangkat lunak yang tinggi.
Karena itu, kerja sama lintas sektor, baik pemerintah maupun swasta, antara BRIN, BPS, BAPPENAS, Kementan, KKP, dunia akademik dan perusahaan penghasil platform, menjadi mutlak.
Kini saatnya melihat ketahanan pangan bukan sekadar dari ladang, tetapi dari peta, piksel, dan pola data. Indonesia tidak kekurangan sumber daya, tetapi membutuhkan satu ekosistem informasi yang saling terhubung.
Jika GeoMIMO berhasil menjadi fondasinya, maka bukan mustahil Indonesia kelak dikenal bukan hanya sebagai lumbung pangan tropis, tetapi juga pusat kecerdasan geospasial pangan dunia.
*) Peneliti di Pusat Riset Geoinformatika dan Pusat Riset Pertanian Tanaman Pangan, BRIN
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY