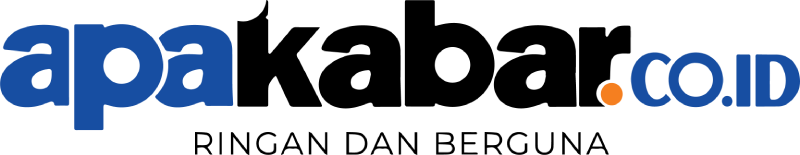OPINI
AI yang Haus: Krisis Air di Balik Revolusi Digital

Oleh: Aswin Rivai*
Dalam imajinasi publik, kecerdasan buatan (AI) sering digambarkan sebagai jalan menuju masa depan yang efisien dan canggih yaitu mampu meningkatkan produktivitas, mengefisienkan layanan publik, hingga mempercepat pertumbuhan ekonomi digital.
Namun, di balik narasi optimisme tersebut, tersembunyi paradoks besar: revolusi digital yang digerakkan AI ternyata sangat haus air.
Air bukan sekadar sumber kehidupan, tetapi kini menjadi bahan bakar tersembunyi dari era digital. Mesin yang melatih dan menjalankan model AI, dari ChatGPT hingga Google Cloud, bergantung pada sistem pendinginan yang membutuhkan jutaan liter air setiap hari untuk mencegah panas berlebih di pusat data (data center).
AI bukan hanya mengonsumsi energi listrik yang besar, tetapi juga memiliki jejak fisik yang nyata dalam bentuk konsumsi air masif, polusi, dan tekanan terhadap ekosistem lokal —isu yang kini mulai mengemuka di banyak negara, termasuk Indonesia.
Laporan Water Atlas dari Heinrich Böll Foundation (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan pesat pusat data AI telah memperparah kekeringan di berbagai wilayah dunia, mulai dari Chile hingga Afrika Selatan.
Di Uruguay, protes besar terjadi setelah Google mengajukan izin pembangunan pusat data saat negara itu mengalami kekeringan terparah dalam 70 tahun terakhir. Ironisnya, Google diberi izin mengambil air tawar, sementara masyarakat harus merebus air asin untuk minum.
Studi Greenpeace (2024) memperkirakan konsumsi air global oleh pusat data akan meningkat dari 239 miliar liter (2024) menjadi 664 miliar liter per tahun (2030) setara dengan kebutuhan air lebih dari 10 juta rumah tangga.
Pelatihan model AI seperti GPT-3 saja diperkirakan memerlukan sekitar 700.000 liter air hanya untuk sistem pendingin. Ini belum termasuk air yang digunakan dalam produksi energi listrik dan manufaktur chip semikonduktor.
Dengan kata lain, semakin besar model AI yang dikembangkan, semakin besar pula biaya ekologisnya dan air adalah komponen utama yang tidak terlihat dalam neraca ekonomi digital.
Jejaknya di Indonesia
Indonesia, dengan populasi digital terbesar keempat di dunia, kini menjadi medan baru ekspansi infrastruktur data global. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo tengah membangun Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, serta memberikan izin bagi sejumlah perusahaan besar seperti Google, Amazon Web Services (AWS), dan Microsoft untuk membuka pusat data di Batam, Bekasi, dan Tangerang.
Namun, di balik ambisi menjadi “poros ekonomi digital ASEAN”, muncul kekhawatiran mengenai daya dukung lingkungan dan ketersediaan air.
Batam menjadi lokasi strategis karena kedekatannya dengan Singapura dan konektivitas internet global. Namun, pulau ini memiliki kapasitas air baku yang terbatas. Sumber utama air Batam berasal dari tiga waduk besar: Duriangkang, Sei Harapan, dan Tembesi.
Menurut BP Batam (2023), kapasitas suplai air bersih maksimum hanya sekitar 3.000 liter per detik, dan 90% sudah terserap untuk kebutuhan industri serta rumah tangga. Pembangunan satu pusat data besar dapat mengonsumsi ratusan ribu liter air per hari, terutama untuk sistem pendingin server. Jika tidak diatur dengan cermat, Batam bisa menghadapi defisit air dalam satu dekade ke depan.
Wilayah Bekasi dan Cikarang, yang menjadi lokasi PDN serta sejumlah proyek data center swasta, menghadapi penurunan muka tanah dan pencemaran air tanah akibat eksploitasi berlebihan. Data dari Badan Geologi (2022) menunjukkan penurunan muka tanah di beberapa area industri Bekasi mencapai 10–15 cm per tahun.
Konsumsi air besar dari industri digital berisiko memperburuk situasi. Ironisnya, sebagian besar air yang digunakan untuk pendinginan server berasal dari air tanah dalam, yang seharusnya menjadi cadangan strategis untuk kebutuhan manusia saat kekeringan.
Ketika Jawa semakin padat dan rentan terhadap krisis air, pemerintah mulai melirik kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara sebagai lokasi alternatif data center berenergi hijau. Namun, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) menunjukkan bahwa proyek besar yang bergantung pada energi dan air bisa menimbulkan tekanan ekosistem hutan dan sungai, terutama jika sistem pendingin masih bergantung pada air permukaan.
Banyak peneliti menyebut fenomena ini sebagai “kolonialisme digital”. Jika di masa lalu negara berkembang menjadi sumber bahan mentah seperti karet, nikel, dan minyak, kini yang diekstraksi adalah air dan energi untuk menopang infrastruktur digital perusahaan raksasa dunia.
AI dan pusat data memang menjanjikan kemajuan teknologi, tetapi manfaat ekonominya sering terkonsentrasi pada korporasi global di Global North, sedangkan biaya ekologisnya ditanggung oleh masyarakat Global South, termasuk Indonesia.
Pola yang sama terlihat: masyarakat lokal menanggung polusi, kelangkaan air, dan kenaikan harga tanah, sementara lapangan kerja yang diciptakan relatif sedikit dan tidak sebanding dengan nilai investasi.
Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP, 2022), Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
Namun, tidak ada satu pun regulasi yang secara tegas mengatur penggunaan air dan dampak lingkungan pusat data. Bandingkan dengan Uni Eropa, yang melalui Energy Efficiency Directive mewajibkan pelaporan penggunaan air oleh data center meski hanya sebatas transparansi, belum pada pembatasan.
Indonesia justru berlomba menarik investasi digital dengan insentif pajak dan izin lingkungan yang dipercepat, tanpa menuntut komitmen keberlanjutan yang kuat. Jika tren ini berlanjut, Indonesia berisiko menjadi "zona korban ekologis" dari ambisi ekonomi digital global.
Sebenarnya, sudah ada teknologi pendinginan berkelanjutan yang dapat mengurangi penggunaan air tawar secara signifikan seperti pendinginan udara (air-based cooling), sistem daur ulang air limbah, pemanfaatan air asin atau air hujan, dan teknologi pemulihan panas (heat recovery) untuk digunakan kembali di industri sekitar. Beberapa data center di Finlandia bahkan memanfaatkan air laut dingin sebagai pendingin alami, menghemat jutaan liter air tawar per tahun.
Namun di Indonesia, penerapan teknologi ini masih sangat terbatas. Penyebab utamanya sederhana yaitu air masih murah dan tidak diatur secara ketat, sehingga perusahaan tidak punya insentif ekonomi untuk berinvestasi dalam sistem ramah lingkungan.
Pulau Jawa, yang menampung lebih dari 60% penduduk Indonesia, kini berada dalam kondisi kritis. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa 80% wilayah Jawa mengalami penurunan cadangan air tanah, sementara 35% wilayah berstatus rentan kekeringan ekstrem.
Di tengah situasi itu, pembangunan pusat data baru di kawasan Bekasi, Karawang, dan Tangerang justru menambah tekanan. Jika tidak ada kebijakan konservasi air yang ketat, kita bisa menghadapi kompetisi air antara manusia dan mesin dalam waktu dekat.
Pertanyaan kuncinya Adalah apakah pembangunan ekonomi digital harus mengorbankan keberlanjutan lingkungan? Untuk menjawabnya, Indonesia perlu menata ulang strategi pembangunan data center dengan menempatkan daya dukung air sebagai variabel utama dalam setiap izin proyek.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan mewajibkan audit air (water audit) untuk semua pusat data baru, memberlakukan tarif air industri progresif agar perusahaan terdorong berhemat.
Mengintegrasikan teknologi daur ulang air dan pendinginan udara sebagai syarat perizinan, melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam penilaian dampak lingkungan (AMDAL) dan transparansi publik mengenai penggunaan air dan energi tiap data center. Kebijakan seperti ini akan menegaskan bahwa kedaulatan digital tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kedaulatan ekologis.
AI membawa janji besar bagi masa depan ekonomi Indonesia dari efisiensi birokrasi, transformasi industri, hingga kemajuan pendidikan. Tetapi, kemajuan tersebut hanya akan berarti jika dibangun di atas pondasi keberlanjutan ekologis. Air adalah hak publik, bukan sekadar input industri. Maka, pembelaan terhadap sumber air bukanlah anti-teknologi, melainkan upaya mendefinisikan ulang arti kemajuan yang sejati: kemajuan yang tidak menghancurkan fondasi kehidupan itu sendiri.
Revolusi AI memang tak terhindarkan. Namun, seperti setiap revolusi sebelumnya, ia menuntut keseimbangan baru antara ambisi dan tanggung jawab. Jika Indonesia ingin menjadi pemimpin ekonomi digital di Asia Tenggara, maka bangsa ini harus berani memimpin bukan hanya dalam inovasi, tetapi juga dalam etika lingkungan dan tata kelola air digital.
Kita tidak bisa membiarkan masa depan di mana server dingin, tapi bumi makin panas; data mengalir lancar, tapi air bersih makin langka.Tantangan abad ke-21 bukan hanya menciptakan AI yang cerdas, tetapi juga AI yang bijak terhadap planetnya.
*) Pemerhati Ekonomi dan Dosen FEB UPN Veteran Jakarta
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY