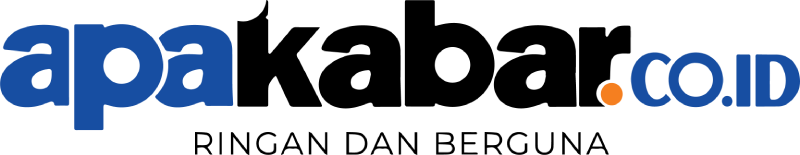NEWS
Belajar Kedaulatan Pangan dari Sedulur Sikep
Ketahanan dan kemandirian pangan warga Sedulur Sikep merupakan buah dari sikap mempertahankan tanah dan tradisi ajaran Samin.

Oleh: Achmad Rizki Muazam
Hamparan sawah nan hijau memanjakan mata di pagi hari. Desir sungai mengalir terdengar sayup dari kejauhan. Pepohonan tumbuh subur menjulang. Kandang hewan peliharaan menghiasi setiap sudut rumah.
Begitulah sekilas pemandangan Dukuh Blimbing, Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Di kampung itu tinggal ratusan keluarga adat Sedulur Sikep.
Kelompok Sedulur Sikep atau juga dikenal suku Samin, tersebar di Blora, Kudus, Pati, Bojonegoro, dan beberapa daerah di Jawa Timur. Mereka menganut ajaran Saminisme, yang menolak budaya kolonial dan kapitalisme serta berprinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam.

Pencetus ajaran Saminisme adalah Samin Surosentiko. Ia dulu melawan penjajah dengan menolak membayar pajak dan tidak mau diperbudak menjadi buruh tani di perkebunan Belanda.
Prinsip dan api perlawanan Samin, masih terus diwariskan oleh Sedulur Sikep di Dukuh Blimbing. Di era gempuran ekonomi global ini, Sedulur Sikep tak terbawa arus.
Mereka konsisten mempertahankan prinsip kedaulatan pangan. Tiap keluarga Sedulur Sikep memenuhi pangannya sendiri dengan bertani. Masing-masing keluarga punya sawah dengan luasan bervariasi: puluhan meter hingga hektaran.
Sedulur Sikep tanam padi tadah hujan, yang tak hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber pengairan, tapi irigasi sungai buatan Pramugi Prawiro Wijoyo–pemangku adat Sedulur Sikep.
Menurut Pramugi, warga di desanya bisa panen padi tiga kali dalam setahun. Sekali panen mencapai 12-13 ton dari lima hektar sawah. Hasil panen tidak mereka jual, hanya dikonsumsi sendiri.

Mbah Pram saat ditemui di pendopo Sedulur Sikep, akhir Januari lalu. Foto: Apakabar.co.id/Achmad Rizki Muazam.
Prinsip Samin, pangan pokok tak boleh dijual. Mbah Pram, sapaan akrab Pramugi bilang, padi hanya boleh dijual kalau kebutuhan pangan keluarga dan tetangga sudah terpenuhi.
Artinya, sisa padi di akhir tahun, jelang panen kembali, kalau masih melimpah baru boleh dijual. “Banyak orang luar cari beras ke sini. Mereka bilang, beras di sini kualitasnya bagus,” ujar Mbah Pram saat ditemui di pendoponya beberapa waktu lalu.
Selain padi, mereka juga tanam sayuran seperti kacang panjang, bayam, cabe, hingga kangkung. Juga tanam buah-buahan seperti melon dan semangka. Mbah Pram bilang, semua kebutuhan pangan Sedulur Sikep berasal dari tanah sendiri!
Bagi Sedulur Sikep tanah merupakan barang istimewa yang harus dilindungi. Prinsip mereka tanah tidak boleh dijual; barang sejengkalpun dengan alasan apapun! “Kalau bisa ya beli lagi, bukan malah dijual,” tegas pria yang kini berusia 67 tahun.
Saking berdaulatnya pangan, Mbah Pram menekankan pada warganya jangan sampai menjadi ‘NU’, alias Nunut Urip. Sebuah istilah dalam bahasa Jawa, berarti: menumpang hidup!
Bagi Mbah Pram, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri, hanya bisa beli ke orang lain, merupakan wujud dari numpang hidup.
Ia mengkritik pola hidup orang kota, kerja tiap hari demi hasilkan uang untuk beli makan. Meski bisa makan, orang kota menggantungkan sumber pangan pada orang lain. Mbah Pram bilang bahwa orang kota tidak mandiri secara pangan!
Dia mengatakan, bentuk kemandirian hidup sesungguhnya ialah mampu memenuhi sumber pangan sendiri. Pram bilang, seperti apa yang dirinya dan Sedulur Sikep lakukan.
Sedulur Sikep tak hanya bertani. Mereka juga beternak ayam, ikan, kambing, hingga sapi. Hewan ternak itu untuk penuhi sumber protein hewani warga. Semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi sendiri.
Mbah Pram bilang, warga jarang belanja ke pasar. Ia contohkan, jika warga tidak punya cabai, mereka akan saling tukar komoditi dengan tetangga.
“Kalau pingin ikan asin atau tahu gitu, baru beli (ke) pasar,” ujarnya.
Sementara kebutuhan hidup lain, seperti biaya sekolah anak dan biaya kesehatan, Sedulur Sikep menjual hasil panen jagung ke pabrik untuk pakan ternak. Di lahan Perhutani, yang berada di belakang perkampungan, mereka tanam jagung pakan.
Mbah Pram misalnya, ia tanam jagung di lahan seluas lima hektar. Sekali panen bisa mencapai 5 ton, dengan harga jual tak menentu: Rp3 ribu hingga Rp5 ribu per kilogram.
Kambing Etawa jadi Tabungan
Nariah sedang memotong pohon lamtoro: daun dan batang ia pisahkan. Daun untuk pakan kambing etawa, batang dibakar untuk penghangat kambing kala malam hari di musim hujan.
Ia memelihara empat ekor kambing etawa: tiga berusia dewasa siap potong, satunya baru berusia setahun. Kambing jadi tabungan keluarga Nariah. Jika butuh uang, kambing dijual dengan harga Rp1 juta hingga Rp5 juta, tergantung bobotnya.
“Kadang sampai besar belum ada kebutuhan ya belum dijual. Kalau ada kebutuhan mendadak, kecil ya dijual karena nggak punya uang,” ujar Nariah saat ditemui di rumahnya.
Kambing etawa biasa dijual kalau ada kebutuhan mendesak, seperti untuk tambahan biaya anak sekolah, atau biaya berobat jika anggota keluarga sakit.

Sepanjang mata memandang hampir semua rumah di Dukuh Blimbing terdapat kandang kambing etawa. Kandang-kandang itu terletak di samping atau belakang rumah, berukuran variatif tergantung jumlah ekor yang dipelihara.
Kandang terbuat dari kayu, dengan bentuk panggung: menurut warga, ini berguna untuk hindari kambing terkena penyakit atau virus dan bakteri.
Saban sore hari, batang pohon lamtoro dibakar, lalu ditaruh di bawah kandang. Efek asap pembakaran diyakini warga bisa menghindari kambing terkena penyakit, dan melindungi dari gigitan nyamuk, juga sebagai penghangat saat malam hari.
Mbah Pram bilang, pelihara kambing etawa sudah menjadi kebiasaan Sedulur Sikep di Dukuh Blimbing. Dirinyalah yang pertama kali beternak kambing etawa pada tahun 1986.
Saat itu, menurut Mbah Pram, ternak kambing etawa di Kabupaten Blora, khususnya Dukuh Blimbing sebuah anomali. Kambing etawa dipercaya hanya bisa dipelihara di daerah dataran tinggi bersuhu dingin; sementara cuaca Blora panas.
“Kalau di Jawa Barat di Garut, kalau di Jawa Tengah di Purworejo, kalau di Jawa Timur di Ponorogo,” ucapnya.
Berkat usaha Mbah Pram, kini kambing etawa banyak dipelihara Sedulur Sikep di Dukuh Blimbing. Setiap keluarga pasti pelihara, jumlahnya variasi: terbanyak mencapai 40 ekor. Mbah Pram sendiri pelihara 26 ekor.
Saking melimpahnya jumlah kambing etawa, tak heran kalau para pengepul kerap datang membeli. “Kamu cari kambing 3 ribu ekor di sini, nggak usah pilih-pilih jantan atau betina, monggo, tiga jam selesai.”
Bahkan tidak hanya pengepul, pejabat kabupaten hingga orang dari Malaysia beli kambing etawa di Dukuh Blimbing. “Itu orang Malaysia beli sampai Rp6 juta per ekor,” ujar Mbah Pram.
Bukan hanya daging, kotoran kambing etawa juga menghasilkan uang. Warga mengolah kotoran menjadi pupuk, dijual seharga Rp50 ribu per karung. Sebagian digunakan sendiri untuk pupuk jagung.
Omon-Omon Food Estate
Prabowo Subianto gencar mengkampanyekan “ketahanan pangan.” Ia bahkan mencanangkan swasembada pangan dengan mencetak sawah baru (food estate) di luar Jawa hingga 3 juta hektar dalam kurun waktu 4 tahun ke depan.
Ketua Umum Partai Gerindra ini menargetkan Indonesia swasembada beras pada tahun 2027, menjadi eksportir beras pada 2028, dan menjadi lumbung pangan dunia pada 2029.
Pemerintah canangkan program pangan nasional yang disebut food estate, sebuah usaha pangan terintegrasi meliputi: usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, maupun usaha industri pada kawasan dalam skala luas.

Salah satu lokasi food estate dilakukan di Papua, terletak di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Yahukimo, dengan total luas 2.684,680,68 hektar.
Kritik dilontarkan Mbah Pram terkait program food estate tersebut. Dia mengatakan, keberagaman pangan di Indonesia lebih baik, daripada menyeragamkan menjadi makan nasi.
“Yang suka singkong ya biarkan singkong, yang sagu ya sagu. Yang makan jagung ya biarkan jagung,” ujarnya.
Menurut Mbah Pram, swasembada pangan bisa terlaksana kalau masyarakat di masing-masing daerah bercocok tanam pangan lokal. Bukan membuka lahan di daerah orang, tapi masyarakatnya tidak memakan beras.
Eko Cahyono, peneliti Sajogyo Institute menilai, pemerintah salah kaprah dalam paradigma swasembada pangan. Menurut dia, semestinya pemerintah tidak menganut mazhab atau aliran “ketahanan pangan.”
Eko menjelaskan tiga mazhab teori pangan. Pertama, ketahanan pangan atau food security. “Kalau ketahanan pangan yang penting ada pangannya. Mau dari industri skala besar, mau dari impor, mau dari korporasi, mau dari oligarki, nggak masalah, yang penting ada pangannya.”
Kedua, kemandirian pangan atau food independen. Teori ini mengutamakan pengelolaan pangan bersumber dari dalam negeri, yang terpenting bukan dari asing atau impor.
Namun, menurut Eko, produsen pangan dalam teori ini kerap dikuasai oleh pengusaha besar bercorak oligarki. Teori ini mengabaikan apa yang disebut kapitalisme from below atau kapitalisme dari bawah.
“Jadi, anti asing itu harus dicek juga. Memang kalau yang nggak asing, nggak kalah berutalnya? Wah ngeri juga itu!” tegasnya.
Ketiga, kedaulatan pangan atau food sovereignty. Eko mengatakan, teori ini memberikan otonomi penuh terhadap petani dalam memproduksi pangan dari hulu sampai hilir.
Ia menyebut, data Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) menunjukkan, 65% pangan di Indonesia dipenuhi oleh pertanian keluarga.
“Kenapa yang dimanjakan korporasi kalau yang memenuhi pangan nasional itu adalah pertanian keluarga?” ujar Eko.
Eko lantas menegaskan bahwa, food estate sebagai politik ketahanan pangan nasional adalah sesat pikir. Argumen utama pemerintah terhadap food estate, menurutnya, pasti karena dunia akan mengalami krisis pangan, sehingga Indonesia perlu lumbung pangan.
“Kalau krisis pangan karena apa? Pernah gak kita periksa? Ternyata akar kekurangan pangan kita itu akibat dari konversi lahan besar-besaran, dari lahan produktif pangan menjadi sawit dan tambang,” ucap Eko.
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY