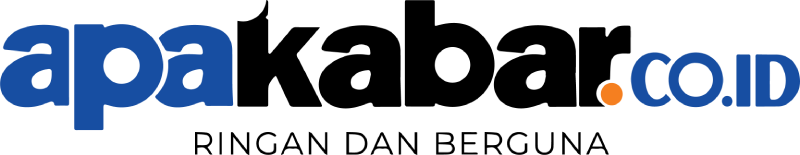OPINI
Menjawab Tantangan Diaspora Muda Indonesia di Panggung Global

Oleh: Aris Heru Utomo*
Setiap 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda, sebuah peristiwa bersejarah ketika para pemuda pada tahun 1928 berikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia. Ikrar itu lahir dari semangat menolak sekat-sekat kedaerahan dan melawan kolonialisme untuk membangun identitas nasional yang menyatukan.
Dari semangat itulah, kelak tumbuh tekad untuk memerdekakan Indonesia. Tanpa persatuan para pemuda, termasuk mereka yang belajar di Belanda seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Nazir Datuk Pamoentjak, kemerdekaan Indonesia mungkin masih menjadi cita-cita yang tertunda.
Hampir seabad kemudian, pemuda Indonesia kembali tersebar di berbagai belahan dunia. Namun, kali ini bukan untuk berjuang melawan penjajahan bersenjata, melainkan menghadapi bentuk baru kolonialisme yaitu ketergantungan ekonomi, dominasi budaya, dan ketimpangan global.
Dalam konteks inilah semangat Sumpah Pemuda perlu diterjemahkan ulang, bukan hanya sebagai nasionalisme dalam batas geografis, tetapi juga dalam semangat global citizenship. Pemuda Indonesia yang berada di luar negeri bukan sekadar berperan sebagai pelajar atau menjadi pekerja migran, tetapi mereka telah menjadi duta nilai-nilai bangsa yang dapat memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.
Menurut data Kementerian Luar Negeri, lebih dari sembilan juta warga Indonesia kini bermukim di luar negeri, sebagian besar di antaranya berusia muda. Mereka menempuh pendidikan di berbagai universitas internasional, bekerja di perusahaan global, atau berkiprah di bidang teknologi dan ekonomi kreatif.
Banyak di antara mereka menjadi ilmuwan di laboratorium riset Eropa, animator di studio film Hollywood, atau pendiri startup di Singapura dan Dubai. Mereka membawa narasi baru tentang Indonesia sebagai bangsa yang kreatif dan berdaya saing global.
Tantangan utamanya kemudian adalah bagaimana negara menjaga hubungan emosional dan profesional dengan para pemuda tersebut.
Kekhawatiran tentang brain drain atau keluarnya tenaga terampil dari Tanah Air, seharusnya diubah menjadi peluang brain network yaitu terjalinnya jejaring pengetahuan yang justru memperkuat kapasitas nasional seperti yang dilakukan antara lain oleh Korea Selatan, India, dan China.
Mereka telah membuktikan bahwa diaspora dapat menjadi jembatan dalam inovasi, investasi, dan transfer teknologi.
Upaya itu sebenarnya mulai terlihat melalui pembentukan Indonesian Diaspora Network (IDN) pada 2012. Namun, keberadaan jaringan diaspora Indonesia ini perlu diperkuat menjadi ekosistem kolaboratif antara pemerintah, kampus, dan komunitas diaspora muda. Alih-alih sekadar menyerukan agar mereka "pulang", negara seharusnya membuka ruang kontribusi dari mana pun mereka berada.
Sebuah kebijakan berpandangan global perlu ditata, bukan hanya berupa pendataan diaspora, tetapi sistem yang menautkan mereka ke sektor strategis seperti sains, diplomasi, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Dengan begitu, setiap anak muda Indonesia di luar negeri bisa tetap terhubung dalam satu ekosistem kebangsaan yang hidup dan produktif.
Lebih dari itu, diaspora muda juga memiliki peran besar dalam soft diplomacy. Di tengah meningkatnya sentimen identitas dan politik global yang keras, mereka dapat menjadi jembatan budaya.
Komunitas mahasiswa Indonesia di Jepang, Belanda, atau Amerika Serikat, misalnya, kerap memperkenalkan batik, gamelan, kopi Nusantara, hingga wayang dalam festival lokal. Tanpa mandat diplomatik formal, mereka menjalankan diplomasi kultural yang efektif, memperkenalkan Indonesia sebagai bangsa yang terbuka dan berbudaya tinggi.
Era media sosial memperluas peran itu. Seorang content creator diaspora misalnya, bisa menjangkau jutaan penonton lintas negara hanya dengan satu video tentang kuliner Indonesia atau cerita perantauan. Dari sinilah muncul bentuk baru "Sumpah Pemuda Digital", generasi muda yang bersatu dalam identitas meski tersebar di berbagai belahan dunia.
Agar semangat ini berlanjut, perlu sinergi lintas lembaga. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bisa membangun program mentoring lintas negara bagi mahasiswa dan profesional muda. Kampus dalam negeri dapat membuka kolaborasi riset bersama alumni diaspora.
Sementara, organisasi kepemudaan pun dapat menginisiasi Sumpah Pemuda Global Forum sebagai wadah tahunan untuk mempertemukan anak muda Indonesia dari seluruh dunia, berbagi gagasan, dan membangun jejaring.
Langkah-langkah seperti ini bukan sekadar seremoni, tetapi investasi strategis bagi diplomasi masa depan. Dunia kini tak lagi ditentukan oleh kekuatan militer, melainkan oleh jejaring pengetahuan, teknologi, dan narasi.
Pada akhirnya, ketika berbicara tentang Sumpah Pemuda, maka kita tidak bicara tentang sebuah dokumen sejarah yang beku, melainkan janji yang terus hidup. Pada 1928, para pemuda bersumpah melampaui sekat suku dan bahasa. Pada 2025, generasi muda perlu menambahkan satu sumpah lagi yaitu bersatu dalam jejaring, berinovasi lintas batas, dan berkontribusi bagi kejayaan Indonesia di dunia global.
Di tangan diaspora muda, nasionalisme menemukan bentuk barunya yaitu bukan sekadar mencintai tanah air dari dalam, tetapi memperkenalkan tanah air ke dunia dengan cara yang cerdas, kreatif, dan kolaboratif.
Sebagaimana para pemuda 1928 menjahit benang merah identitas nasional, kini generasi global Indonesia menjahit jejaring pengetahuan dunia dengan benang nilai-nilai bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
*) Maheswara Utama (Pengajar Utama) Pancasila BPIP
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY