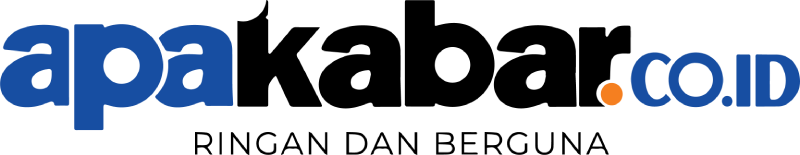OPINI
Tata Kelola Penyimpanan Beras yang Berkualitas

Oleh: Entang Sastraatmadja*
Membicarakan beras di Indonesia tidak pernah sekadar membicarakan hasil panen. Bahasan ini selalu membawa dimensi politik, ekonomi, dan kedaulatan bangsa.
Terlebih tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia yang berhasil mencatat produksi beras melimpah hingga diprediksi mencapai 34,6 juta ton oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA).
Sebuah capaian yang membanggakan, terutama ketika dunia tengah dihantui krisis pangan global. Pemerintahan Presiden Prabowo pun berani menegaskan kebijakan tanpa impor beras, langkah yang merepresentasikan kepercayaan diri terhadap kemampuan produksi nasional dan kemandirian petani dalam negeri.
Namun kebanggaan itu bisa kehilangan maknanya jika rantai pascapanen, terutama sistem penyimpanan dan tata kelola cadangan beras, masih rapuh dan tidak profesional.
Indonesia berpeluang besar menjadi raksasa beras ASEAN, tetapi peluang itu bisa berubah menjadi beban jika manajemen stok tidak dikelola dengan cermat.
Produksi yang tinggi tanpa pengelolaan pascapanen yang baik hanya akan melahirkan paradoks ketika beras melimpah tetapi sebagian rusak di gudang, sementara harga di pasar tetap fluktuatif.
Di sinilah titik kritis tata kelola penyimpanan beras menjadi isu strategis. Gudang Bulog sebagai simpul utama penyimpanan cadangan beras pemerintah (CBP) sering kali menjadi sorotan karena temuan beras berkutu, berbau apek, dan kualitasnya turun.
Kondisi ini menandakan bahwa keberhasilan produksi tidak otomatis berarti keberhasilan pengelolaan. Produksi yang melimpah hanya akan bermakna jika diimbangi oleh sistem penyimpanan yang efisien, higienis, dan berbasis teknologi.
Kritiknya jelas bahwa selama ini perhatian pemerintah lebih banyak terpusat pada aspek hulu, yakni peningkatan produksi dan pengendalian harga, sementara aspek hilir mulai dari penyimpanan, distribusi, hingga pengendalian mutu masih dipandang sebagai urusan administratif.
Padahal di sinilah letak kerentanan terbesar. Ratusan ribu ton beras impor pernah dilaporkan rusak di gudang Bulog akibat hama. Bukan karena produksi yang salah, melainkan karena manajemen penyimpanan yang tidak sesuai standar.
Jika Indonesia ingin mempertahankan swasembada beras dan membangun sistem ketahanan pangan yang kokoh, maka paradigma ini harus diubah. Pengelolaan stok beras harus dilihat sebagai bagian integral dari sistem pangan nasional, bukan sekadar fungsi logistik.
Dalam konteks kebijakan publik, penyimpanan beras sebenarnya menyentuh banyak dimensi strategis meliputi efisiensi fiskal, stabilitas harga, keamanan pangan, bahkan diplomasi pangan.
Setiap ton beras yang rusak di gudang sesungguhnya adalah pemborosan negara dan kegagalan perlindungan terhadap petani. Karena itu, solusi tidak bisa sekadar administratif seperti memperbaiki regulasi atau memperbanyak gudang.
Berbasis Data
Yang diperlukan adalah pendekatan teknologi, tata kelola berbasis data, dan model kemitraan yang memperkuat ekosistem pangan dari hulu ke hilir.
Pemerintah sejatinya sudah memiliki sejumlah regulasi tentang pengelolaan cadangan beras, namun implementasinya masih belum seragam di lapangan.
Di sinilah urgensi koordinasi lintas sektor menjadi krusial. Cadangan beras nasional tidak hanya tanggung jawab Bulog, tetapi juga pemerintah provinsi, kabupaten, dan bahkan desa.
Desentralisasi pengelolaan pangan yang berbasis kebutuhan lokal bisa menjadi langkah revolusioner untuk mengurangi beban logistik nasional dan memperpendek rantai distribusi.
Ketahanan pangan tidak harus selalu diukur dari stok di gudang pusat, tetapi dari kemampuan daerah mempertahankan ketersediaan pangan di level masyarakat.
Langkah lain yang tak kalah penting adalah modernisasi infrastruktur penyimpanan. Banyak gudang Bulog dibangun pada dekade 1980-an dan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan standar penyimpanan modern.
Teknologi pengatur suhu dan kelembapan yang seharusnya menjadi standar kini masih jarang diterapkan secara konsisten.
Pemerintah perlu mempercepat transformasi digital di sektor pangan melalui sistem informasi manajemen gudang berbasis real-time monitoring, yang memungkinkan kondisi gudang termasuk suhu, kelembapan, dan stok diketahui setiap saat. Dengan demikian, intervensi bisa dilakukan lebih cepat sebelum kerusakan terjadi.
Kualitas penyimpanan juga tidak bisa dilepaskan dari kualitas bahan baku yang diserap. Bulog harus memastikan bahwa gabah yang dibeli dari petani sudah memiliki kadar air dan mutu sesuai standar.
Di sinilah pendidikan pascapanen bagi petani menjadi kunci. Ketika petani memahami cara pengeringan yang tepat, penyimpanan di tingkat gudang pun akan jauh lebih efisien.
Oleh karena itu, kebijakan pangan harus dipadukan dengan program pemberdayaan petani yang melibatkan penyuluh, perguruan tinggi, dan lembaga riset.
Inovasi teknologi pengeringan gabah, misalnya dengan sistem solar dryer dome atau mechanical drying system, harus diperbanyak di sentra-sentra produksi padi agar kadar air gabah bisa distandarkan sebelum diserap Bulog.
Sementara itu, manajemen pergudangan perlu menerapkan sistem First-In-First-Out (FIFO) secara disiplin. Pola rotasi stok yang baik akan mencegah akumulasi beras lama yang rawan rusak.
Di samping itu, pengawasan internal harus diperkuat melalui audit mutu secara periodik dengan melibatkan pihak independen agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan stok meningkat.
Kepercayaan Publik
Tata kelola yang baik tidak hanya soal efisiensi logistik, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap lembaga pangan negara.
Untuk menjadikan Indonesia benar-benar berdaulat pangan, perlu dibangun paradigma baru: bahwa keberhasilan pangan bukan diukur dari banyaknya produksi, tetapi dari kemampuannya menjaga mutu, nilai, dan keberlanjutan.
Swasembada pangan abad ke-21 tidak cukup ditandai oleh kemandirian produksi, melainkan juga oleh kapasitas sistem logistik dan penyimpanan yang modern, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berbasis inovasi teknologi.
Tantangan yang dihadapi Indonesia hari ini sesungguhnya adalah peluang untuk melompat lebih jauh. Beras yang melimpah adalah simbol kemakmuran, tetapi tanpa sistem penyimpanan yang tangguh, simbol itu mudah kehilangan makna.
Ketahanan pangan sejati lahir dari ketekunan mengurus setiap detail dari sawah hingga gudang, dari butir gabah hingga distribusi di meja makan rakyat.
Ketika sistem penyimpanan berjalan efisien, petani memperoleh harga yang layak, negara memiliki stok yang aman, dan rakyat mendapatkan beras yang berkualitas.
Inilah bentuk nyata kedaulatan pangan yang tidak hanya membanggakan di atas kertas, tetapi juga menyejahterakan di kehidupan nyata.
Kebijakan pangan Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan. Antara menjadi bangsa produsen beras yang berdaulat atau sekadar negara agraris yang bergantung pada sistem penyimpanan usang.
Jalan yang ditempuh akan menentukan masa depan kedaulatan pangan negeri ini. Saatnya pemerintah, Bulog, dunia akademik, dan masyarakat bersinergi memperbaiki seluruh rantai tata kelola beras secara menyeluruh.
Sebab keberhasilan pangan bukan sekadar tentang berapa banyak beras yang dihasilkan, melainkan tentang seberapa cerdas bangsa ini menjaga hasil panen agar tetap bermakna bagi seluruh rakyatnya.
*) Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY