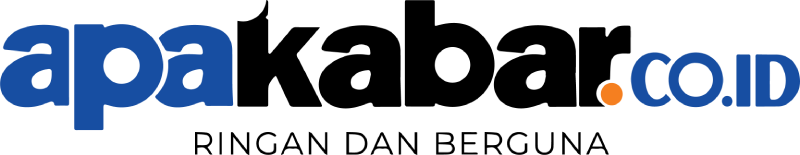OPINI
WNA Menjadi Direktur BUMN: Debat Kompetensi vs Tata Kelola

Oleh: Achmad Nur Hidayat*
Kontroversi muncul ketika Presiden Prabowo Subianto membuka peluang ekspatriat memimpin BUMN. Pertanyaannya, apakah warga negara asing mampu menjadi obat mujarab bagi kinerja BUMN?
Saya memandang inti persoalannya bukan paspor, melainkan tata kelola, budaya organisasi, dan insentif. Regulasi baru memberi Badan Pengelola BUMN wewenang mengecualikan syarat WNI , sehingga paspor bukan penghalang.
Namun retorika yang menempatkan WNA sebagai juru selamat justru menutupi akar masalah sebenarnya. BUMN memegang peran strategis sebagai pengelola listrik, pelabuhan dan pabrik semen.
Kinerja mereka mempengaruhi belanja negara dan pasokan energi masyarakat. Karena itu, perdebatan tentang direksi tidak sekadar tentang paspor, tetapi tentang bagaimana memastikan perusahaan negara ini menjalankan mandat ekonomi dan sosial dengan efektif.
Untuk mempermudah topik yang rumit, bayangkan BUMN sebagai pasien yang sakit. Sakitnya bukan karena genetika, tetapi pola hidup buruk: diet tidak sehat (model bisnis tak efisien), jarang berolahraga (minim inovasi), dan lingkungan kotor (tata kelola buruk).
Mengganti dokter lokal menjadi dokter asing tanpa memperbaiki pola hidup tidak akan menyembuhkan pasien. Begitu pula, mengganti direksi dengan WNA tanpa membenahi struktur dasar tidak akan menyembuhkan BUMN.
Data dan Realitas Kinerja
Program transformasi BUMN 2019–2021 meningkatkan pendapatan dan laba secara signifikan berkat reformasi tata kelola dan pelibatan investor. Namun sebagian besar BUMN masih terjebak proteksi; hanya segelintir perusahaan menyumbang mayoritas dividen dan banyak lainnya terlilit utang.
Masalah utama adalah struktur insentif dan budaya proteksi yang membuat kegagalan jarang dihukum, bukan minimnya talenta.
Riset atas transformasi ini mencatat pendapatan BUMN tumbuh 18,8 % dan laba konsolidasi melonjak lebih dari delapan kali lipat, dari Rp 13 triliun menjadi Rp 124,7 triliun.
Di sisi lain, contoh negatif tetap banyak: Krakatau Steel yang dulu jaya kini terlilit utang Rp 28 triliun , laba Semen Indonesia merosot dari lebih dari Rp 5 triliun menjadi sekitar Rp 500 miliar , dan 97 % dividen negara berasal dari delapan BUMN besar.
Itu berarti ratusan entitas lain justru menjadi beban. Kenyataan ini menekankan bahwa tanpa reformasi insentif dan budaya, kehadiran talenta asing pun tidak akan banyak membantu.
Narasi WNA sebagai Solusi
Perubahan regulasi memungkinkan ekspatriat memimpin BUMN. Penunjukan mereka hendaknya dipandang sebagai upaya memperoleh keahlian spesifik, bukan solusi universal. Sejumlah BUMN pernah menempatkan WNA di jajaran direksi , namun hasilnya tidak spektakuler. WNA tidak otomatis lebih bebas korupsi; tanpa tata kelola kuat, siapa pun bisa terseret praktik buruk.
Penunjukan dua ekspatriat di Garuda Indonesia pada 2025 menjadi contoh terkini. Pemerintah berharap profesional dari maskapai global membawa perspektif baru untuk memperbaiki keuangan perusahaan setelah restrukturisasi. Publik harus menuntut transparansi target kinerja, karena tanpa perubahan sistem mereka pun akan terbebani warisan masalah lama.
Argumentasi dan Rekomendasi
Analisis ekonomi kelembagaan menyoroti tiga hal: insentif yang salah memicu moral hazard; monopoli dan proteksi menumpulkan kompetisi serta inovasi ; dan tata kelola buruk mengundang praktik korupsi.
Menarik talenta asing tanpa mengubah ketiganya hanya mengganti pemain tanpa mengubah permainan. Langkah konkret meliputi reformasi proses seleksi direksi dengan kriteria transparan , memisahkan penugasan publik dari bisnis komersial, serta melepaskan proteksi—termasuk mengurangi jumlah BUMN dan mendorong merger, kemitraan strategis, riset, digitalisasi, dan pelatihan.
Pengalaman transformasi 2019–2021 membuktikan bahwa menekan praktik “katebelece” dan menerapkan remunerasi berbasis kinerja mampu mendorong laba.
Oleh karena itu, memperkuat dewan komisaris, audit independen, sistem pelaporan anonim, dan transparansi pengadaan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari reformasi.
Masyarakat dan DPR harus mengawasi implementasi reformasi ini agar tidak berhenti pada wacana. Tanpa dukungan kebijakan lintas sektor, upaya memperbaiki BUMN akan mudah tergelincir dan memudar di tengah jalan.
Debat WNA vs WNI sebetulnya menutupi isu yang lebih besar: tata kelola dan insentif. Kehadiran WNA di pucuk pimpinan BUMN bukan hal baru , dan data menunjukkan keberhasilan transformasi bergantung pada reformasi sistem, bukan paspor.
Masyarakat berhak menilai penunjukan ekspatriat di Garuda Indonesia sebagai langkah mencari keahlian spesifik, namun harus menuntut transparansi target dan perbaikan struktural. Tanpa perombakan sistem, analogi dokter asing mengobati pasien tanpa mengubah gaya hidup akan terwujud—pasien tetap sakit.
Sebagai ekonom, saya menyerukan fokus pada reformasi mendasar: memperbaiki insentif, menumbuhkan kompetisi, dan memperkuat tata kelola. Penugasan sosial mesti dikompensasi, remunerasi direksi dihubungkan dengan pencapaian, regulasi membuka inovasi, dan audit ditingkatkan.
Hanya dengan langkah‑langkah tersebut BUMN dapat bertransformasi dari beban menjadi lokomotif pertumbuhan, pencipta lapangan kerja, dan sumber kebanggaan nasional. Perubahan memang memerlukan waktu dan keberanian, tetapi melanjutkan status quo jauh lebih mahal bagi perekonomian dan kepercayaan publik.
*) Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY