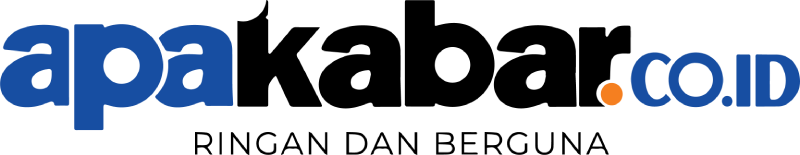OPINI
Matinya Otoritas: Kala Semua Orang Menjadi Ahli di Era Digital

Oleh: Bustomi*
Di era media sosial, setiap orang bisa berbicara apa saja, entah itu tentang politik, agama, ekonomi, bahkan ilmu kedokteran, tanpa harus memiliki latar belakang keilmuan yang memadai.
Demokratisasi informasi yang semula dimaksudkan untuk memperluas akses terhadap pengetahuan, kini menjelma menjadi ironi, yakni banjirnya opini, tanpa otoritas. Fenomena ini oleh Tom Nichols (2017) disebut sebagai "kematian otoritas keilmuan".
Ironi ini semakin kentara ketika kita berbicara tentang agama, khususnya Islam. Di dunia digital, siapa pun bisa menjadi ustaz, kiai, atau pemikir Islam. Cukup dengan ring light, kamera ponsel, dan kutipan potongan ayat, seseorang dapat memperoleh ribuan, bahkan jutaan pengikut dan menjadi rujukan umat.
Padahal, dalam tradisi Islam klasik, otoritas keilmuan dibangun melalui rantai panjang sanad (sandaran), penguasaan metodologi, dan legitimasi dari para guru/kiai/ustaz/ulama sebelumnya.
Otoritas ilmu dalam Islam tidak pernah lahir secara instan. Ia dibangun dari sistem sanad keilmuan yang kokoh, yang merupakan rantai transmisi ilmu dari guru ke murid, dari generasi ke generasi.
Dalam tradisi keilmuan Islam, setiap disiplin memiliki imam-imam otoritatif. Imam otoritatif itu, dalam qira’at ada Imam Nafi’, Asim, dan Abu Amr; lalu dalam fiqih dikenal empat imam besar, yaitu Abu Hanifah, Malik, al-Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal; bahkan dalam hadits, ada nama-nama besar, seperti al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi, menjadi simbol otoritas yang tak tergoyahkan.
Sementara dalam bidang akidah, banyak tokoh, seperti Abu Hasan al Asy’ari dan Abu Mansur al-Maturidi, yang menata bangunan teologis Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kecermatan nalar dan kedalaman dalil; atau dalam tasawuf, ada Junaid al-Baghdadi dan al-Ghazali, yang menyatukan jalan batin dan akal dalam bingkai syariat.
Dari rangkaian nama-nama besar tersebut, kita belajar satu hal, yaitu ilmu tidak pernah bebas nilai dan bebas otoritas. Ia tidak bisa dilepaskan dari sanad, dari sistem pengakuan otoritatif yang memastikan validitas sumber dan keabsahan pemahaman.
Hanya saja, di era digital, prinsip sanad itu nyaris lenyap. Pengetahuan berpindah tanpa isnad, yang artinya tanpa guru, tanpa disiplin, tanpa tanggung jawab epistemik. Seseorang bisa menonton video berdurasi 60 detik tentang makna tauhid, lalu merasa cukup untuk menasihati umat.
Fenomena TikTok fiqh atau YouTube Theology ini melahirkan apa yang bisa disebut “otoritas bayangan”, yaitu ilusi pengetahuan yang tampak meyakinkan, tetapi dangkal dan sering menyesatkan.
Lebih jauh lagi, algoritma media sosial menciptakan ekosistem, di mana yang paling viral dianggap paling benar. Otoritas keilmuan digantikan oleh otoritas algoritmik.
Jika Imam al-Bukhari membutuhkan ratusan guru dan ribuan perjalanan untuk menyusun sahih-nya, maka kini cukup dengan caption yang menarik dan musik latar yang viral, seseorang dapat dianggap “pakar agama”.
Fenomena ini bukan hanya mengancam struktur otoritas keilmuan Islam, tetapi juga merusak ekosistem sosial umat.
Ketika setiap orang mengklaim otoritas, kebenaran menjadi relatif dan fragmentatif, perdebatan agama berpindah dari majelis ilmu ke kolom komentar, dari kitab ke meme, dari diskusi ilmiah ke perang thread di X (Twitter).
Masalah utamanya bukan pada kebebasan berekspresi, melainkan pada krisis literasi keagamaan. Masyarakat kini cenderung menilai kebenaran, bukan dari hujjah dan sanad, melainkan dari gaya bicara dan kecepatan menjawab.
Padahal, para ulama klasik menempuh jalan panjang dan berat untuk sampai pada derajat otoritas. Imam al-Syafi’i, misalnya, belajar dari puluhan guru lintas wilayah, sebelum menulis al-Risalah, karya monumental tentang ushul fiqih. Imam al-Ghazali baru menulis "Ihya’ Ulumuddin" setelah melewati fase skeptisisme spiritual dan penempaan intelektual yang panjang.
Sementara itu, di dunia digital, seseorang bisa menjadi "influencer keagamaan" hanya karena pandai berdebat dan fasih berbicara. Otoritas bergeser dari ahl al-‘ilm atau orang berilmu menjadi ahl al-likes atau orang yang disukai.
Dalam tradisi Islam, otoritas bukan berarti kekuasaan untuk memaksakan pendapat, tetapi tanggung jawab moral untuk menjaga "kemurnian" ilmu.
Karena itu, pemulihan otoritas keilmuan di era digital, bukan berarti menutup akses publik terhadap ilmu, melainkan menegakkan kembali etika belajar, yaitu talaqqi (menerima langsung), tabayyun (memverifikasi), dan taslim (menyerah/tunduk pada kebenaran) kepada yang ahlinya. Semua bermuara pada pakarnya yang otoritatif.
Hal yang harus diingat adalah, teks tidak pernah berdiri sendiri, tanpa konteks. Ayat atau hadits bisa dimaknai berbeda, tergantung pada maqasid dan otoritas yang menafsirkannya. Di sinilah pentingnya sanad, dimana ia akan menjadi jembatan antara teks dan konteks, antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Tanpa otoritas, ilmu hanya menjadi informasi kosong, tanpa ruh, tanpa hikmah.
Fenomena "matinya otoritas keilmuan", sejatinya bukan hanya kematian pengetahuan, melainkan kebangkitan kesombongan. Orang tidak lagi bertanya kepada yang tahu, karena merasa sudah tahu segalanya. Tom Nichols menyebut ini sebagai era keangkuhan egaliter, dimana fakta, bukti, dan kompetensi dianggap tidak lebih penting dari opini pribadi.
Dalam konteks keislaman, ini berarti kita hidup di masa ketika “taqlid buta” digantikan oleh “ijtihad liar” dimana semua orang merasa berhak menafsirkan agama, tanpa bekal metodologis.
Jika dulu para ulama/ahli mengingatkan bahaya berfatwa tanpa ilmu, maka kini kita menghadapi generasi yang berani menasihati, tanpa guru. Inilah wajah baru kejumudan di era digital, yaitu kebebasan yang kehilangan kedalaman.
Solusinya, tentu bukan membungkam publik, tetapi membangun kembali budaya ta’dzim terhadap ilmu dan ulama. Di tengah arus informasi yang tak terbendung, kita perlu ruang-ruang pendidikan publik yang mengajarkan cara berpikir kritis, tanpa kehilangan adab terhadap otoritas.
Perguruan tinggi, pesantren, dan lembaga pendidikan atau kajian lainnya, harus tampil lebih aktif di ruang-ruang digital. Jika algoritma menjadi medan baru dakwah, maka para ahli harus turun tangan, bukan mundur. Sebab jika ruang kosong dibiarkan, ia akan diisi oleh kebodohan yang berani berbicara dengan percaya diri dan kemudian dipercaya dan diikuti ribuan, hingga jutaan pengikutnya.
Dalam sejarah Islam, ilmu bukan hanya soal hafalan dan pengetahuan, tapi adab dan sanad. Al-Ghazali pernah menulis bahwa ilmu tanpa adab akan menjadi fitnah bagi pemiliknya. Di era digital, barangkali tantangannya bukan lagi bagaimana menguasai ilmu, melainkan bagaimana menjaga adab terhadap ilmu, terhadap pakar atau ahli atau ulama.
Otoritas sejati bukan diukur dari jumlah pengikut, tetapi dari kedalaman sanad dan keluasan hikmah. Dan mungkin, di tengah dunia yang ramai dengan noise, jalan terbaik adalah kembali mendengarkan voice, yaitu bukan tentang siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling dalam ilmunya.
*) Pengurus Lembaga Ta’lif wan Nasyr (LTN) PWNU Jawa Timur dan mahasiswa program doktoral FISIP Universitas Airlangga
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY